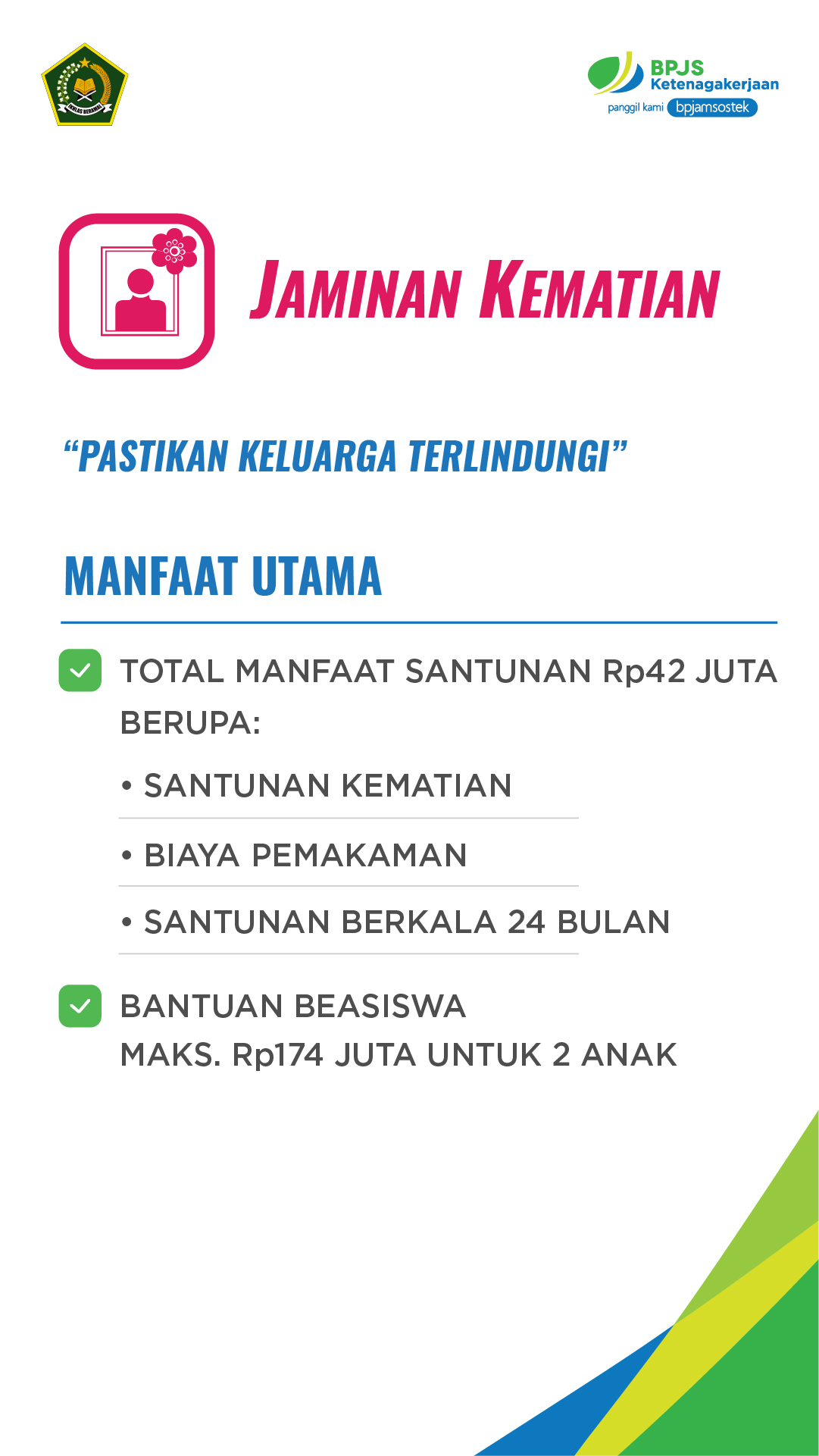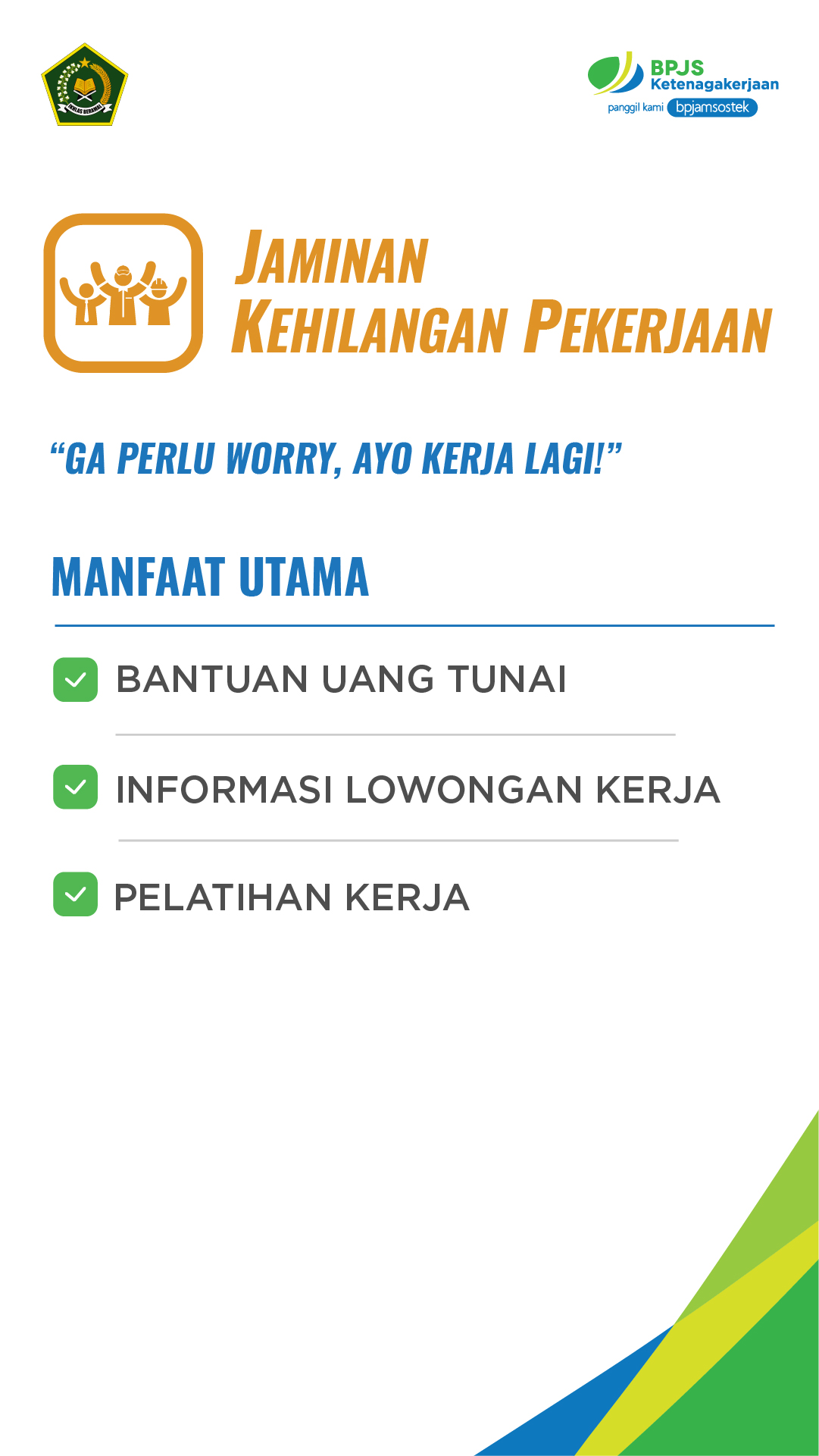Belenggu Disiplin Pendidikan di Papua
B Josie Susilo Hardianto, Papua (kompas)
Frans Wakei, guru SMP Negeri Bomomani itu, duduk termangu sambil meluruskan kakinya. Ia baru saja memulangkan semua siswa dari dua kelas, padahal jarum jam belum genap menunjuk pukul 11.00. Di daerah pedalaman Papua, seperti di Kabupaten Dogiyai, perilaku disiplin, misalnya, belum sepenuhnya datang dari guru.
Frans berkata, guru pengajar hari itu tidak datang sehingga siswa-siswa terpaksa dipulangkan. Yang memprihatinkan, itu bukan yang pertama kali ia lakukan. Kerap kali siswa dipulangkan jauh sebelum pukul 13.30, waktu resmi murid meninggalkan sekolah.
Siang itu hanya tiga kelas diampu dua guru honorer dan seorang guru tetap, padahal seharusnya ada 15 guru yang mengajar. Kepala sekolah pun, tutur Frans, seperti biasanya, tidak hadir. ”Ini yang membuat disiplin guru kian luntur dan sekolah perlahan hancur sudah,” kata Frans.
Beberapa kelas SMP Negeri Bomomani—eks wilayah Kabupaten Nabire itu—tak terurus. Jendela tak lagi tertutup kaca. Ada satu ruang di ujung deretan kelas hancur berantakan. Kertas berserak dan baunya minta ampun. ”Maaf, anak-anak sering menggunakan ruang di sebelahnya untuk buang air karena memang tidak ada kamar mandi di sekolah ini,” tutur Frans.
Dana bantuan operasional sekolah hingga kini juga tidak jelas pengelolaannya. Begitu pun dengan bantuan lain, seperti enam unit komputer dari Kementerian Komunikasi dan Informatika, jaringan telepon, dan internet. Meski semua perangkat itu terpasang berikut sistem penerima dan parabolanya, tak satu pun yang aktif. Bahkan, pembangkit listrik tenaga matahari yang menjadi sumber energi sistem tersebut telah lama hilang.
Praktis, alat-alat itu tidak pernah beroperasi sejak dipasang. Yang mengherankan, dengan situasi dan kondisi seperti itu, setiap kali kelulusan angkanya mencapai lebih dari 90 persen. Tidaklah mengherankan jika ada guru yang mengeluhkan kemampuan siswa SD, SMP, atau SMA yang masih sulit membaca atau berhitung. ”Memang itu faktanya. Kuantitas lebih utama dibanding kualitas,” kata Frans.
Kondisi runyam itu diakui terus terang oleh Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Dogiyai Andreas Yobee. Salah satu soalnya adalah disiplin guru, siswa, atau orangtua murid. Banyak guru tidak disiplin dan itu langsung memengaruhi anak didik. Di sisi lain, belum banyak orangtua memahami makna pendidikan.
Sejak sekolah pendidikan guru (SPG) dihapus, menurut Andreas, sulit menemukan guru yang memiliki semangat dan menempatkan tugas keguruan sebagai panggilan. Tak mengherankan, ketika wilayah Lembah Kamu dan Mapiha dimekarkan menjadi kabupaten baru, yaitu Dogiyai, banyak guru meninggalkan sekolah dan jadi pejabat struktural pemerintah daerah yang baru. Padahal, jumlah guru di Dogiyai sangat terbatas.
Menurut Andreas, cara pemerintah mengelola pendidikan di Papua tidak sama dengan cara para misionaris. ”Dulu persekolahan berjalan baik dan bagus. Yayasan Pendidikan dan Persekolahan Katolik (YPPK) serta Yayasan Pendidikan dan Persekolahan Gereja-gereja Injili Papua memperhatikan betul ketersediaan guru dan fasilitas lainnya sebelum membuka sekolah baru. Rumah untuk guru juga disiapkan. Selain itu, mereka secara rutin juga mengontrolnya,” kata Andreas.
Namun, sejak pemerintah membuat banyak sekolah baru melalui program Inpres (Instruksi Presiden), pendidikan di pedalaman Papua justru terbengkalai. Akibatnya, tenaga guru di kedua yayasan terbagi ke sekolah-sekolah baru, dan guru pun tak mau mengajar.
Andreas mengeluh, kerap kali saat ia mengunjungi sekolah di kampung-kampung, ia menemukan siswa hanya mencatat dari buku yang ditinggalkan oleh guru. Itu sebabnya, ia menolak ketika diminta membuat SMK dan SMA baru. ”Karena memang tidak ada guru,” kata Andreas.
Di Dogiyai, sekolah-sekolah baru memang terbangun, tetapi guru tidak ada. Di Dogiyai, umpamanya, ada 63 SD dengan 14.000 siswa, tetapi jumlah guru SD hanya 369 orang. Jumlah guru tidak sebanding dengan jumlah murid.
Bahkan ada SD di Saikoni, Iyago, dan Adauwo yang masing-masing diasuh hanya oleh seorang guru saja!
Ah, ini lagi! Belum terpilihnya bupati Dogiyai definitif sejak kabupaten itu terbentuk empat tahun lalu juga jadi sumber kendala. Penambahan guru dan anggaran tentu saja buntu!
Berbagai kendala administratif dari penyediaan guru, fasilitas, hingga sikap guru seolah belenggu yang menjerat dunia pendidikan di Papua. Akibatnya jelas, Papua tetap tertinggal.
Padahal, nun di sana ada wacana bijak: Non scholae sed vitae discimus, manusia belajar bukan sekadar untuk sekolah, tetapi terutama untuk hidup.
Salah satu tokoh pendidikan kita, J Drost (almarhum), pun sudah mengingatkan: pendidikan itu bukan untuk membelenggu, tetapi untuk membebaskan….
Jadi, apa lagi Pak Menteri?