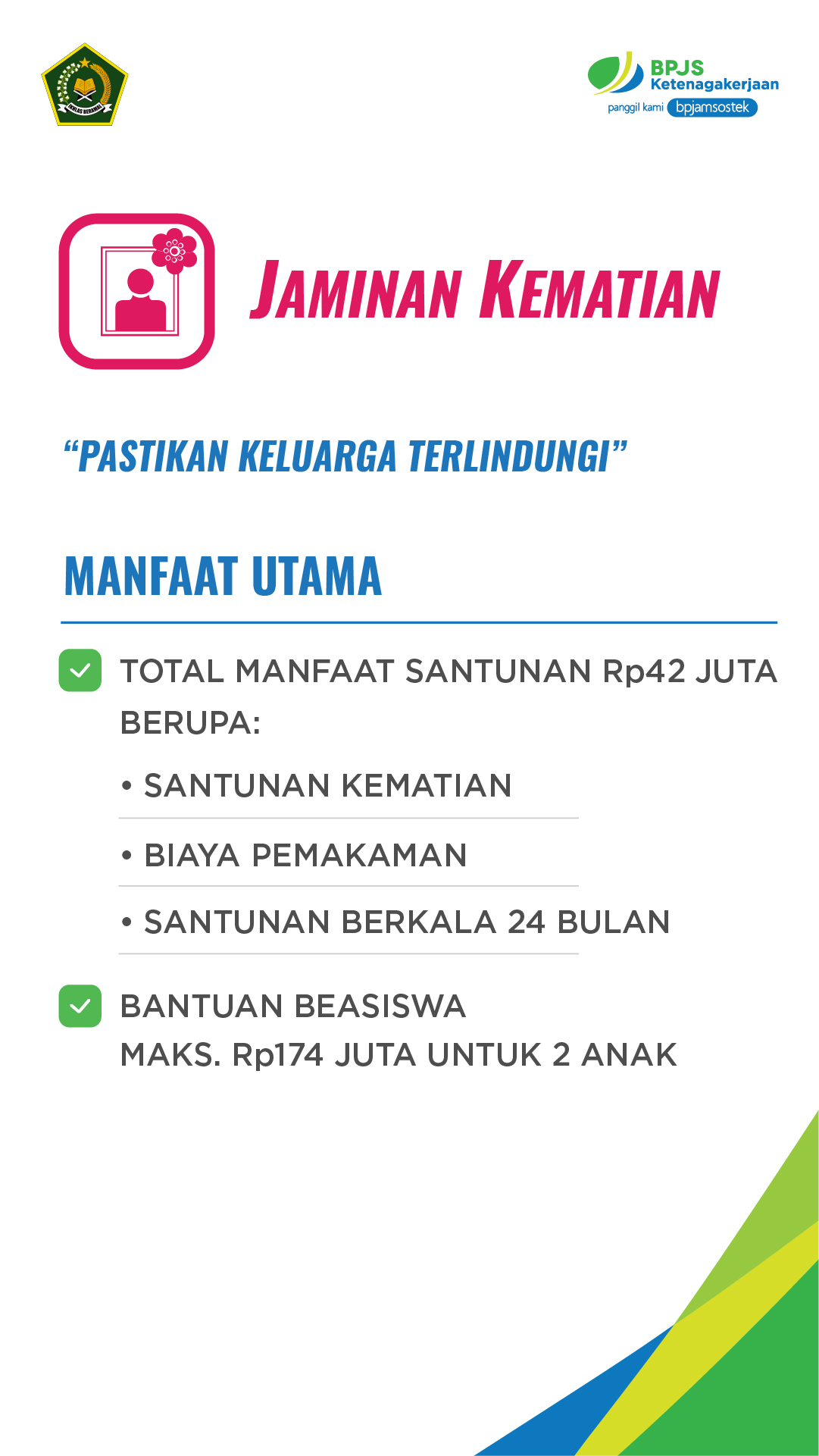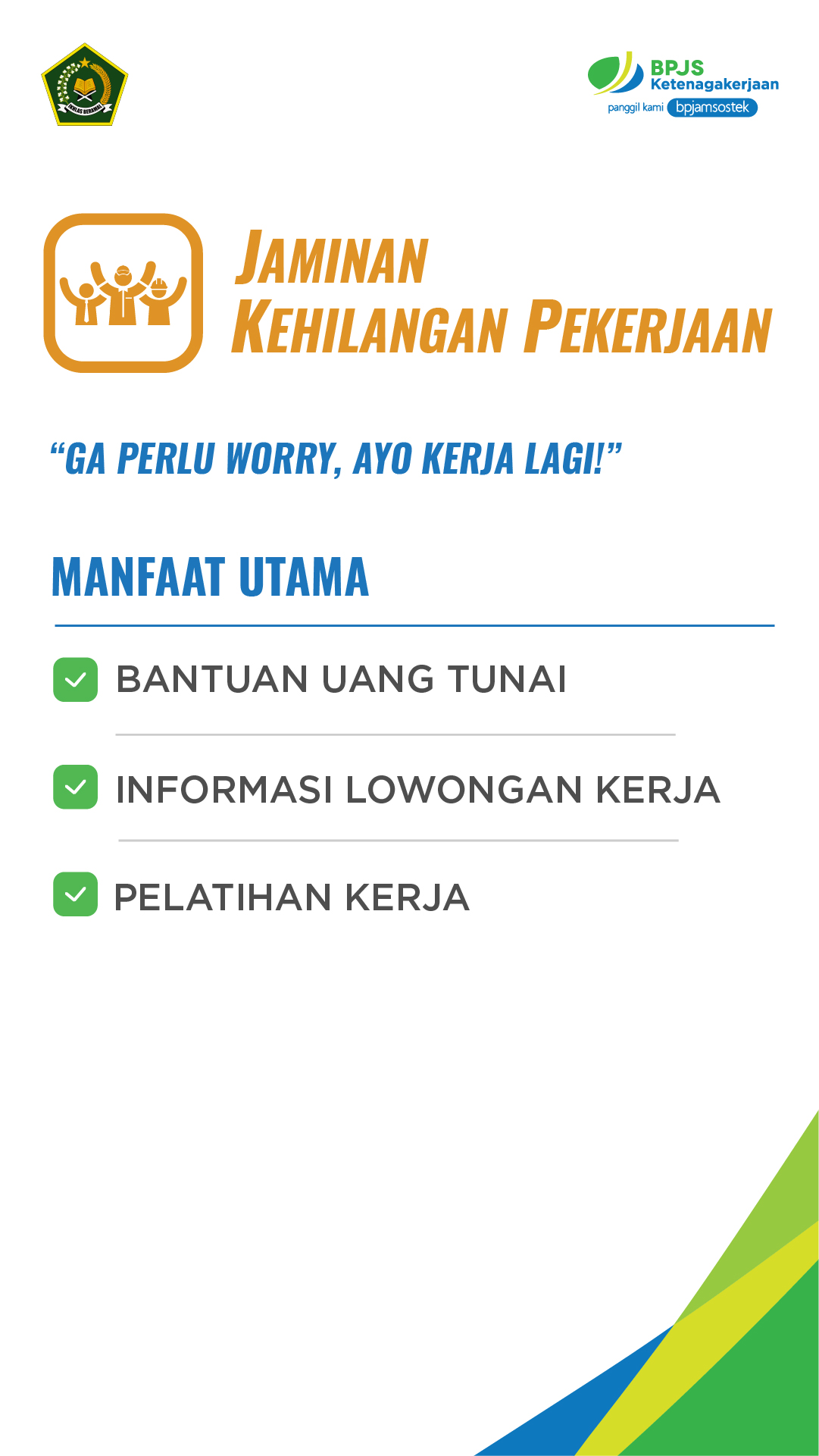Humaniora Digital dan Kesantunan
Wacana (Suara Merdeka)SEWAKTU kecil, guru mengajarkan dunia ada dua: fana, yaitu dunia yang bisa rusak, yang kita tempati saat ini, dan dunia baka yaitu dunia setelah manusia meninggal dunia. Setelah berumur 46 tahun sekarang ini, saya menyadari ternyata ada dunia baru, yang tidak pernah dibayangkan manusia.
Dunia baru antara dunia fana dan dunia baka itu adalah dunia maya (virtual world), yaitu dunia online luas, yang berisi berbagai lingkungan simulasi interaktif dengan dasar komputer. Dunia maya kini sangat menghegemoni sehingga banyak orang rela meninggalkan dunia fana untuk berlama-lama berkecimpung di dalamnya.
Pelarian dari stres atas berbagai masalah di dunia fana, yang dulu jadi alasan untuk pergi selama-lamanya dari dunia fana ke dunia baka lewat jalan pintas, kini mengarah ke dunia maya, ke berbagai media sosial. Dunia baru itu kadang melupakan humanitas kita sebagai manusia, melanggar batas moral, etika, agama, dan privasi orang lain. Dengan dasar itulah lahir UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
Adapun humaniora yang mencakup teologi, filsafat, hukum, sejarah, bahasa, sastra, kesenian, dan psikologi adalah disiplin ilmu yang dapat menjadikan manusia lebih manusiawi dan berbudaya (KBBI; 1998). Dengan demikian humaniora digital (digital humanities) mengacu adaptasi humaniora dalam dunia komputer, sebagai sumber belajar berbagai ilmu pengetahuan yang bisa membuat manusia lebih berbudaya.
Bagaimana mengaitkan humaniora digital dengan kesantunan? Teori kesantunan berawal dari teori "muka"dalam diri manusia, untuk berinteraksi interpersonal atau interaksi sosial (Erving Goffman; 1959). Muka mengacu harga diri, perasaan, dan segala asosiasi tentang diri seseorang. Interaksi sosial harus mempertimbangkan manajemen muka (face management) sehingga muka orang lain dan muka sendiri tidak terancam atau rusak (Brown dan Levinson; 1987).
Namun, apa yang terjadi dalam humaniora digital selama ini? Dalam interaksi, transaksi, atau pergaulan di dunia maya, humaniora digital yang seharusnya dijaga demi harmonisasi sosial, banyak dilanggar (atau terjadi "perusakan muka" orang lain). Agama kadang dijadikan sarana berebut tahta, filsafat dibuat-buat untuk melaknat, hukum diputarbalikkan supaya terasa lurus, dan kebenaran rekor sejarah dipelesetkan untuk menebar fitnah. Bahasa dan sastra pun acap dibuat jahat untuk mengumpat dan menghujat.
Berujung Perusakan
Dunia maya yang liku-liku jalan setapaknya dipandu kepiawaian mesin pencari (search engines), di antaranya yang terbesar Yahoo dan Google, menjelma menjadi berbagai bentuk media sosial. Sebenarnya kita harus menyikapi dunia maya sebagai ruang publik milik masyarakat luas.
Itu termasuk media sosial populer seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan Youtube sebagai sarana interaksi sosial untuk mencipta, berbagi, dan bertukar gagasan, gambar, dan video dalam komunitas dan jaringan maya. Tentu ruang publiktidak bisa direduksi menjadi pojok informal ruang rumah kita, semisal untuk bergosip, bersenda-gurau, dan berkelakar antarindividu secara akrab, dengan topik apa saja. Kitaharus mempertahankan topik di ruang publik tetap bersifat umum, netral, dan aman, tidak menyinggung, apalagi menghujat pihak tertentu.
Artinya, kita perlu menjaga kesantunann interaksi dan transaksi di ruang publik dunia maya. Bayangkan apa yang terjadi andai tiap pengguna ruang publik, dengan topik apa saja, kemudian bertukar informasi, gambar, atau bahkan aksi, termasuk yang kurang atau tidak senonoh? Ruang publik akan menjadi kotor, risiko "perusakan muka" para pengguna juga tinggi, dan akhirnya pengadilan UU ITE yang menengahi. Beruntung bila konflik itu bisa diakhiri. Seandainya tidak? Disharmoni dan disintegrasi di kalangan masyarakat luas akan tereskalasi. Dalam kasus seperti ini, konflik di dunia maya bisa berpindah ke dunia fana, berujung perusakan nyata atas moral, mental, dan fisik di mana-mana.
Fenomena selfie misalnya, termasuk yang kurang atau tidak senonoh dan berbahaya adalah mengunggah hal pribadi ke ruang publik, dengan tujuan viralitas atau popularitas di dunia maya. Aksi selfie kadang merupakan pelampiasan stres di dunia fana yang menyebabkan kemerebakan pornografi dan pornoaksi. Gara-gara dunia maya kita bisa kehilangan sifat manusiawi, bahkan nyawa sendiri. Humaniora digital yang seharusnya membuat kita lebih berbudaya, justru kehilangan arah, tidak terkendali, dan kontraproduktif.
Humaniora digital seharusnya untuk menjaga nurani, dan mengukuhkan hubungan sosial ke arah harmoni dan integrasi. Termasuk menjaga muka interpersonal dan juga muka sosial: perasaan, harga diri, dan kehormatan bersama. Humaniora digital sejatinya kesantunan digital. (10)
— Dr Jumanto PhD in Linguistics, dosen Fakultas Ilmu Budaya (FIB) Universitas Dian Nuswantoro (Udinus) Semarang