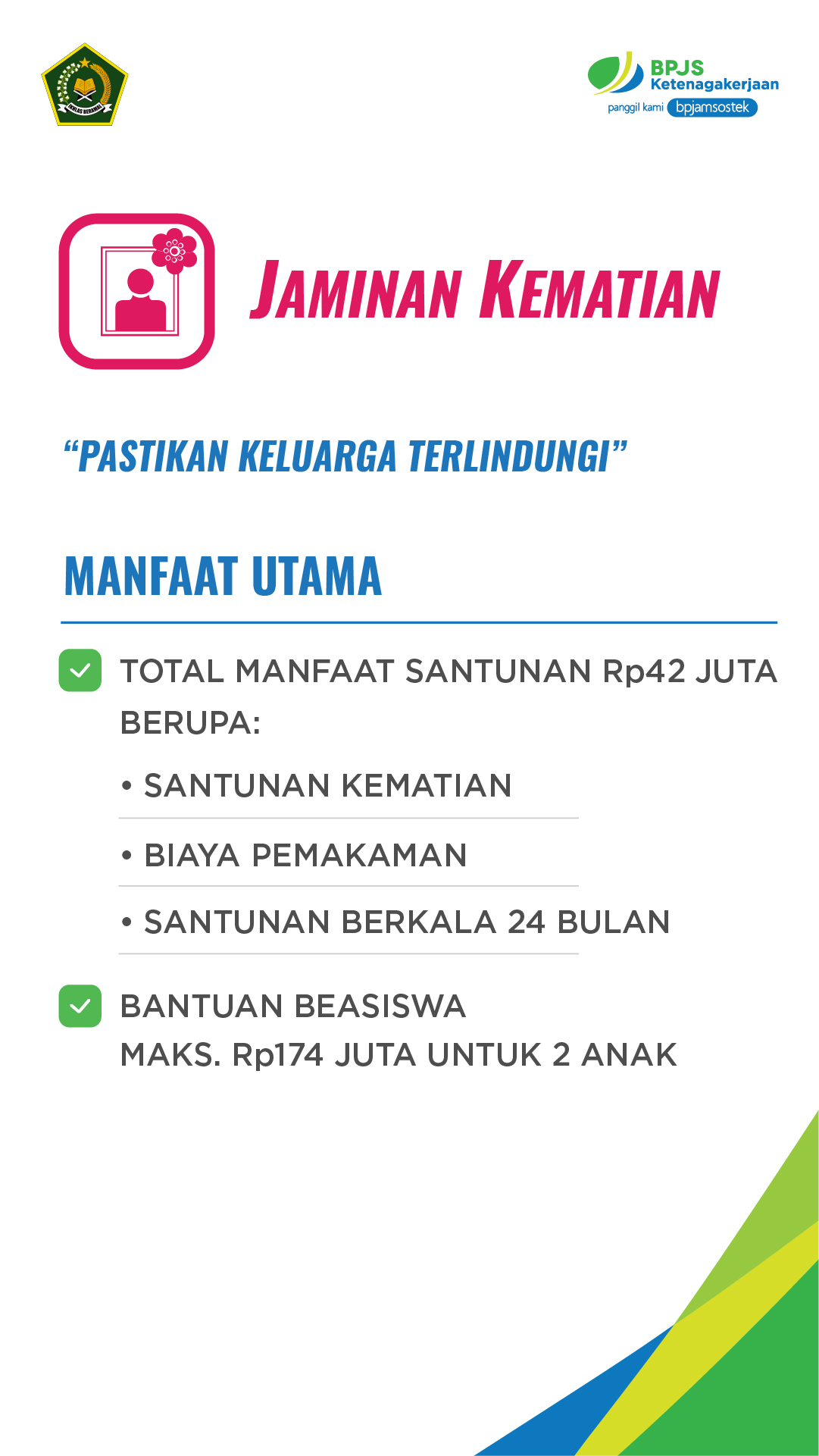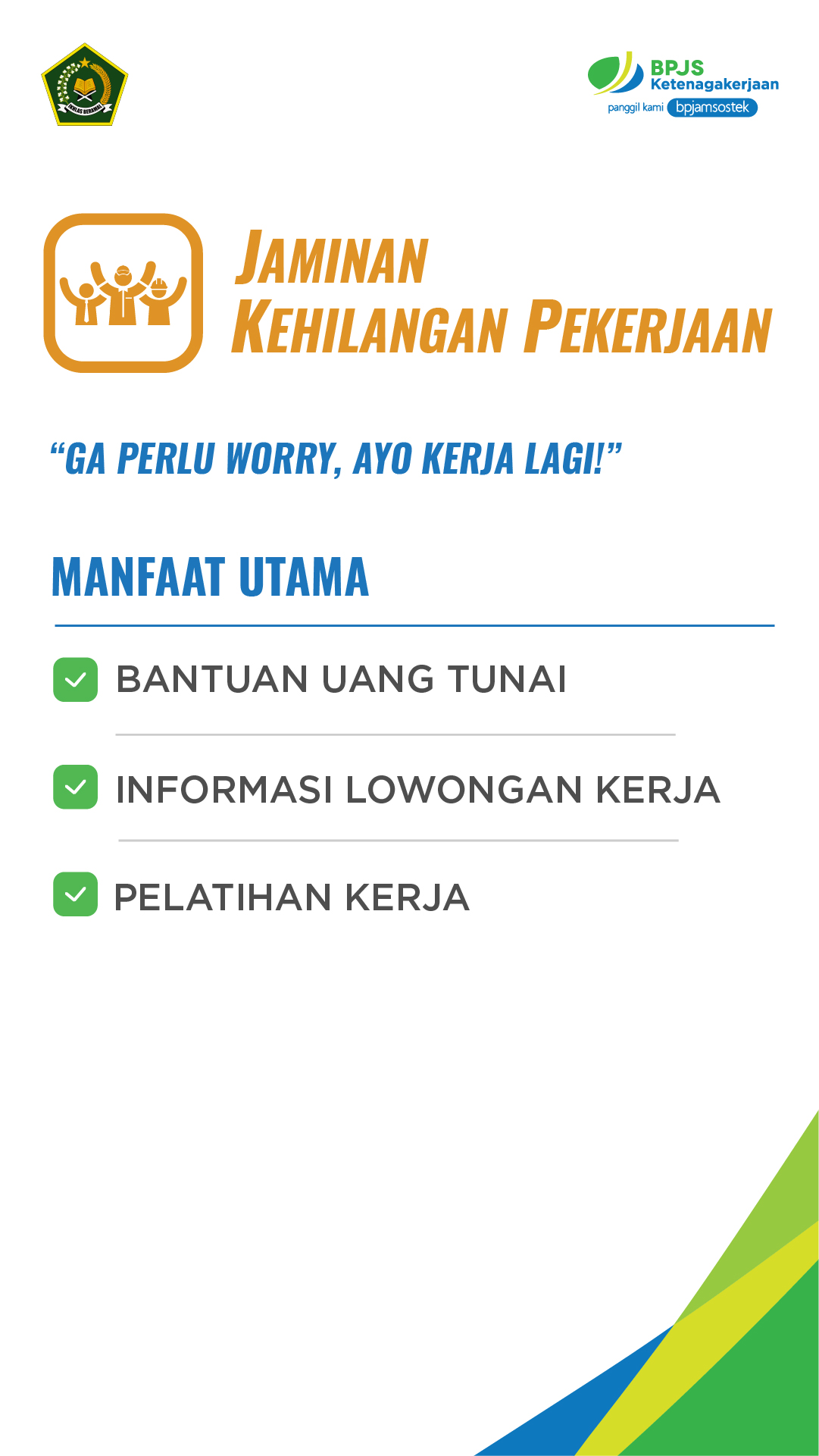Konvensi, Justifikasi Ujian Nasional?
Hampir setiap tahun, menjelang pelaksanaan Ujian Nasional, polemik ujian pengganti Ebtanas sejak 2004 itu seolah-olah menjadi agenda rutin. Kritik, bahkan kecaman yang "menyerang" Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, membuat gerah Mendikbud M Nuh. Untuk mengakhiri pro-kontra yang tak berujung dan menguras energi itu, Kemendikbud berencana menggelar Konvensi Nasional Pendidikan, September mendatang. Salah satunya membahas kebijakan UN.
Tahun ini, gugatan sejumlah pihak yang menghendaki UN dihapus seperti menemukan momentum dengan kisruh penyelenggaraannya. Penundaan UN SMA/ MAN sederajat di 11 provinsi, dan rentetan persoalan lain dinilai banyak pihak sebagai pelaksanaan terburuk sepanjang sejarah UN. Keamburadulan kali ini benar-benar menampar Kemendikbud, dan tidak menutup kemungkinan persoalannya akan berlanjut menyusul dugaan praktik penyimpangan di balik kebijakan ini.
UN kembali menghadapi ujian berat. Pada akhir 2009 keputusan Mahkamah Agung "gagal" membubarkan UN. Tahun ini, kekarutmarutannya membuktikan Kemendikbud belum bisa memenuhi keputusan MA, yakni UN bisa dilaksanakan jika prasyarat dasar seperti sarana-prasarana pendidikan memadai, distribusi dan kualitas guru terpenuhi, serta kurikulum pendidikan akuntabel. Dengan dasar de jure (putusan MA) dan de facto (kisruh UN), tuntutan penghapusan UN memiliki pijakan kuat.
Sejak awal memang ada kontroversi dasar hukum UN. Landasan yuridis antara UU, PP, dan Permen saling bertentangan. Pasal 63 Ayat (1) poin c PP Nomor 19/ 2005 tentang Badan Standar Nasional Pendidikan, dan Permendiknas Nomor 20/ 2005 dinilai bertentangan dengan Pasal 58 Ayat (1) UU Nomor 20/ 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam UU, penilaian hasil belajar bukan hak pemerintah (UN), melainkan oleh pendidik untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan siswa secara berkesinambungan.
Bagaimana tiga fungsi berbeda UN bisa disatukan dalam satu pengukuran aspek kognitif saja yang lemah imajinasi dan intuisi? Kita butuh evaluasi multidimensi dengan beragam instrumen peng-ukuran ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Belum lagi ekses UN, tekanan psikologis siswa, depresi, menurunnya respek siswa pada guru hingga ketidakjujuran. Sesungguhnya kita membutuhkan kajian ilmiah komprehensif tentang UN yang selama ini belum dilakukan.
Kita melihat kebijakan UN lebih merupakan politik anggaran ketimbang pendekatan konsep peningkatan kualitas pendidikan. Sebut saja, dari 20 persen APBN untuk sektor pendikan, faktanya hampir 70 persen untuk membayar gaji. Sisanya baru untuk mutu pendidikan. Anggaran UN yang hampir Rp 600 miliar per tahun, secara skeptik juga lebih terasakan sebagai proyek tahunan. Lalu yakinkah publik UN bakal bisa dihapuskan? Jangan-jangan, ide kovensi hanya untuk justifikasi.