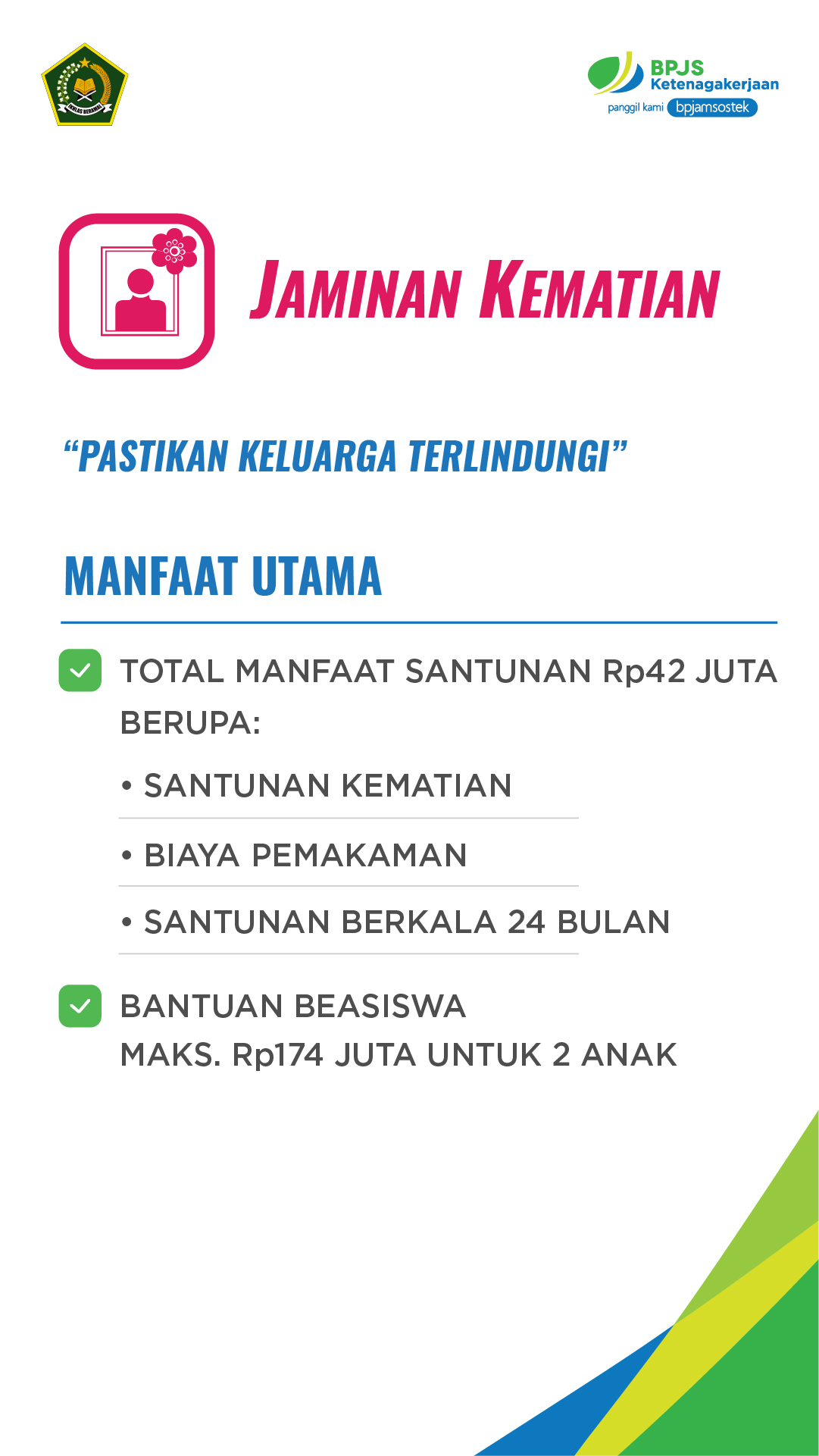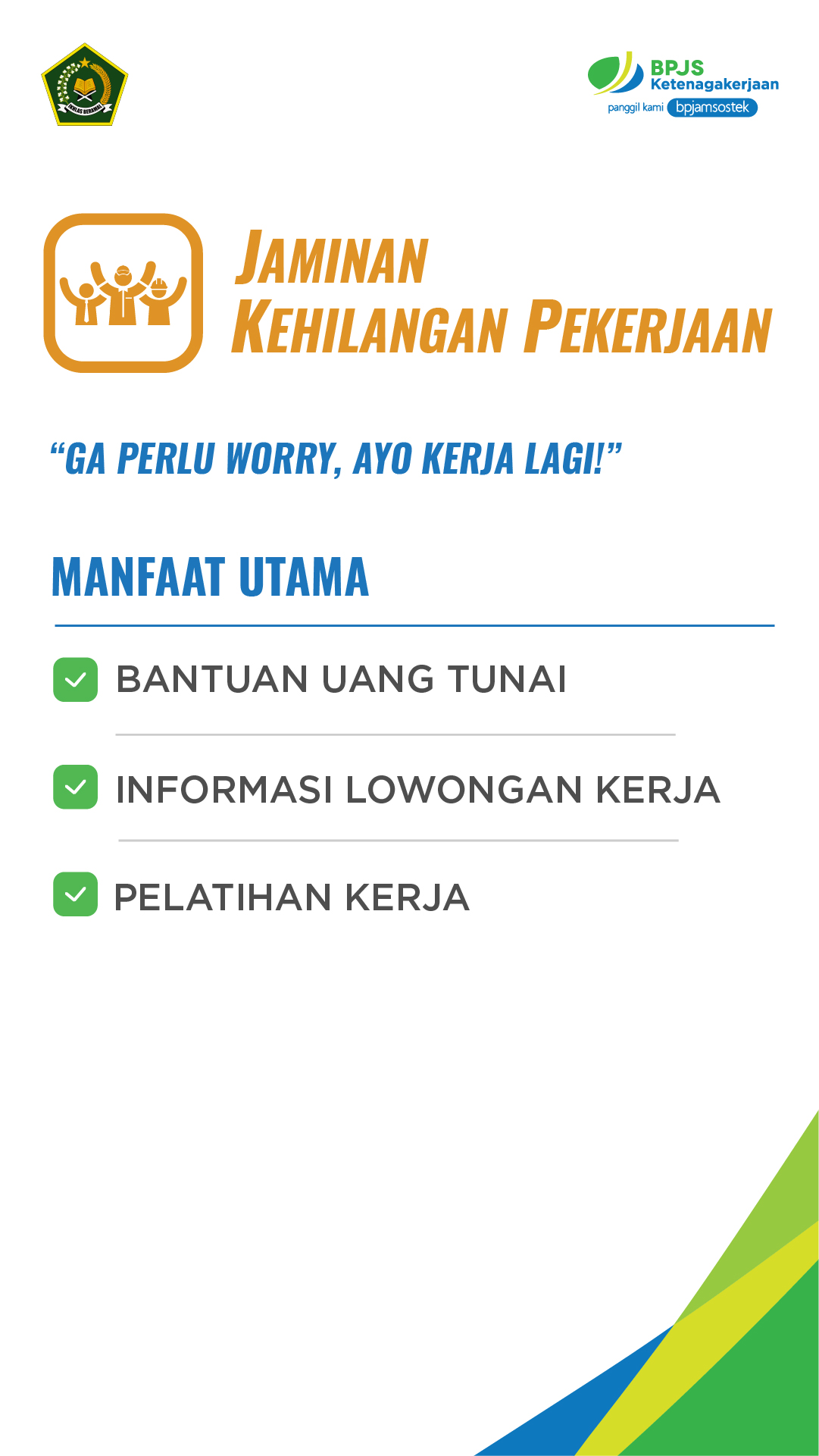Optimisme dari Kompetensi Guru
”Jika guru mau menyikapi secara arif, uji kompetisi itu bisa menggenjot budaya kerja keras dan kerja cerdas”
BERAKIT-RAKIT ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Pepatah ini cocok untuk menggambarkan dinamika kehidupan guru di Tanah Air sehubungan kebijakan baru mengenai sertifikasi guru dan pendidik oleh Kemendikbud. Selain harus memenuhi sejumlah syarat administratif yang cukup rumit, untuk bisa melenggang ke proses sertifikasi, mulai tahun 2012 guru harus lebih dulu lulus ujian kompetensi guru.
Uji kompetensi itu untuk menakar profesionalisme, mendasarkan pada dua poin penting, yaitu penguasaan bahan ajar dan metode pedagogik yang dipakai dalam perancangan pembelajaran. Bila lulus uji kompetensi, peserta berarti mengantongi ”tiket” untuk bisa mengikuti proses sertifikasi, yang saat pertama pelaksanaannya berupa portofolio atau pendidikan pelatihan.
Lolos ujian pertama, belum tentu lolos ujian kedua. Pasalnya, untuk melewati proses sertifikasi juga tidak gampang. Di berbagai daerah, tiap tahun banyak guru peserta sertifikasi tidak lulus. Kini sebelum mereka bisa mengikuti proses sertifikasi, harus menjalani uji kompetisi. Pemerintah menargetkan program sertifikasi berakhir tahun 2015. Tahun ini, kuota sertifikasi hanya 250 ribu untuk sekitar 300 ribu guru peserta uji kompetensi.
Sejatinya, uji kompetensi guru mengandung sisi positif. Pertama; guru bisa bercermin pada nilai yang diperolehnya untuk mengukur derajat keilmuwanannya. Jika skor uji kompetensinya tinggi, hal itu meningkatkan kepercayaan diri (self-confidence). Sebaliknya, yang skornya di bawah rata-rata, tidak perlu merasa tertekan tapi harus bersemangat memperbaiki diri. Pemerintah menetapkan bahwa jika guru tidak lulus uji kompetensi, ada kesempatan mengulang hingga empat kali.
Peningkatan Mutu
Kedua; terbukanya kesempatan mendapatkan pelatihan intensif. Selama ini karena keterbatasan keuangan pemerintah, pelatihan untuk peningkatan profesionalisme belum bisa dinikmati merata oleh guru.
Pemerintah berjanji melakukan langkah terbaik bagi guru yang belum lolos uji kompetensi yaitu dengan menggelar pelatihan. Dengan kata lain, guru tidak dibiarkan belajar sendiri di tengah kesedihan mereka karena belum lulus uji kompetensi.
Ketiga; melahirkan learning-community. Selama ini sekolah lebih kentara sebagai tempat mengajar (teaching) bagi guru dan belajar (learning) bagi peserta didik. Banyak guru membiarkan ilmunya lapuk dimakan oleh zaman dengan indikasi lemahnya minat baca atau minimnya pemanfaatkan perpustakaan sebagai sumber belajar.
Hasil observasi Miftahul Ulum (2011) di sejumlah sekolah di Kabupaten Bogor menunjukkan hal ini; banyak buku (baik dari BOS maupun sumbangan) masih utuh terbungkus plastik dan tertata rapi di lemari. Amat disayangkan, fasilitas itu tidak dioptimalkan pemanfaatannya.
Guru enggan membaca dengan alasan klasik, seperti tidak ada waktu, repot, dan sudah hafal di luar kepala seluruh mata pelajaran. Minat menambah pengetahuan baru sangat rendah sehingga proses pembelajaran di kelas pun monoton dan kurang menarik.
Kita hendaknya optimistis bahwa mekanisme baru berupa uji kompetensi sebagai syarat mutlak menuju proses sertifikasi, jika guru dan pendidik mau menyikapi secara arif, proses kreatif itu bisa menggenjot budaya kerja keras dan kerja cerdas yang dijiwai oleh nilai-nilai kejujuran dan sportivitas untuk menuju pendidikan yang lebih bermutu dan bermartabat. (10)
— Tuswadi MEd, guru Bahasa Inggris SMA Negeri 1 Sigaluh Banjarnegara, kandidat doktor bidang pendidikan pada Graduate School for International Development & Cooperation (IDEC) Hiroshima University Jepang