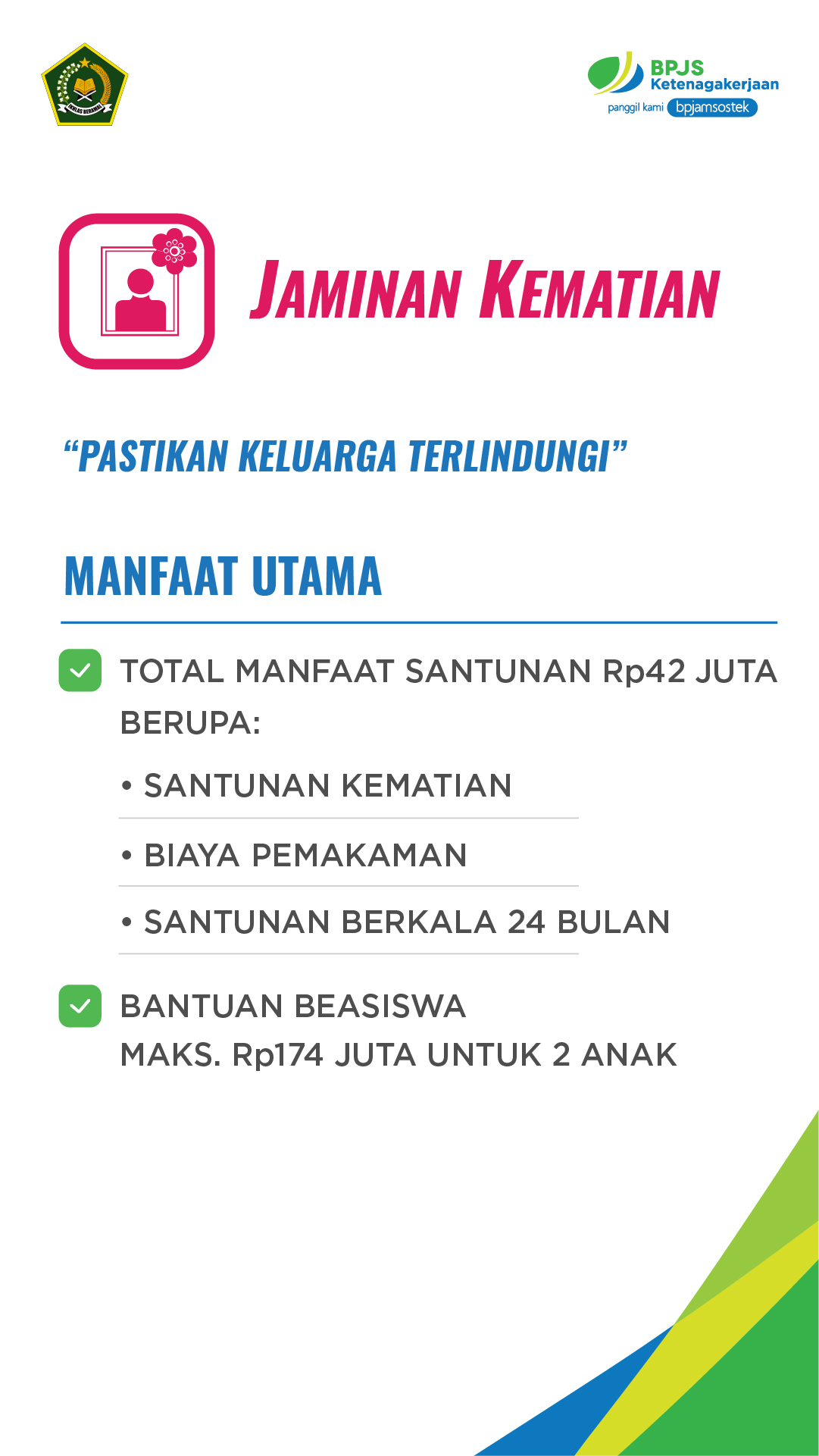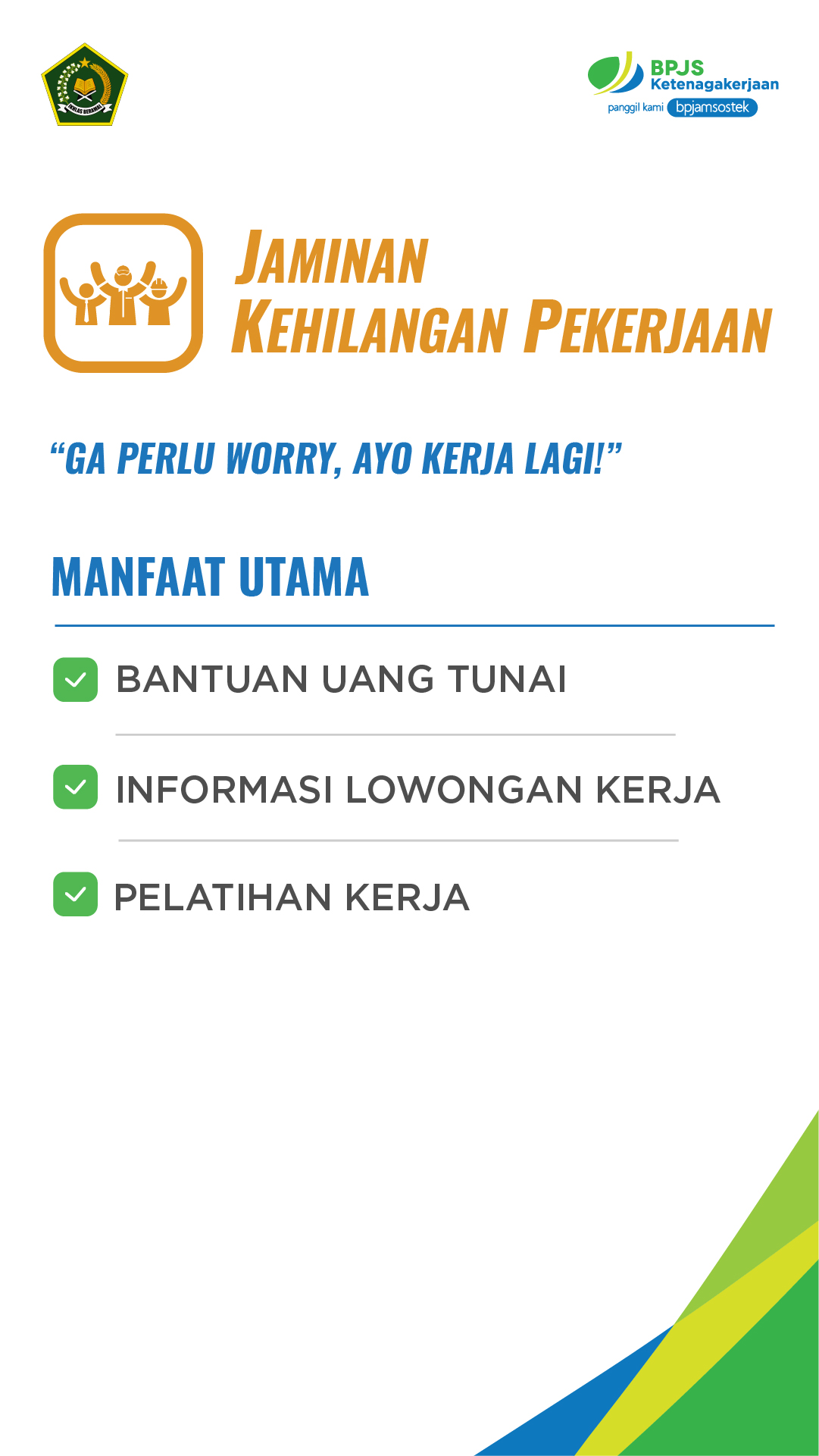Optimistis dengan Pendidikan Perguruan Tinggi Tanah Air
Jakarta (Detik.com)- Beberapa bulan lalu, saya berdiskusi dengan seorang dosen senior sebuah perguruan tinggi top Tanah Air yang sudah sangat paham dengan kondisi pendidikan kita. Menurut dia, kondisi lapangan kerja kita tidaklah separah yang dibayangkan oleh sebagian pengamat. Ada masih banyak orang Indonesia, yang bahkan setelah mendapatkan gelardi negara maju, mereka dengan senang hati memilih untuk pulang ke Tanah Air. Alasan mereka sangat beragam, namun jelas bahwa mereka jauh lebih menyukai lingkungan kerja di Tanah Air, daripada di negara maju.
Faktornya adalah tantangan dan risiko, itulah yang mereka cari. Mereka sudah tidak tertarik dengan kemapanan negara maju, karena sudah tidak ada risiko yang bisa dijinakkan. Mereka ingin ada risiko dan tantangan, karena hanya itulah yang bisa sebabkan mereka melangkah maju.
Tak mengherankan, setelah bekerja sekian tahun di perusahaan, mereka langsung keluar dan mempersiapkan bisnis sendiri. Sebuah fakta menarik, dan bisa jadi rujukan, ditengah kondisi memprihatinkan terjadinya braindrain ke luar negeri (LN). Dapatkah rujukan ini mengubah braindrain menjadi braingain seperti contoh yang diberikan sang dosen senior tersebut?
Keluhan Mengenai Pendidikan Tinggi
Sudah sering terdengar berbagai keluhan mengenai sistem pendidikan tinggi kita yang langsung membandingkan dengan sistim di LN, yang dianggap lebih superior dalam segala hal. Mulai dari keharusan membayar SPP/ berbagai iuran yang terlalu tinggi, Absennya program teaching/ research assistant seperti di LN, lamanya waktu yang diperlukan seorang mahasiswa untuk selesaikan program doktor (umur 30 belum menjadi doktor), lamanya waktu yang diperlukan untuk menjadi guru besar (umur 40 belum menjadi guru besar), Program Pascasarjana hanyalah menjadi sapi perahan dosen, dan mudahnya mencari pekerjaan akademis di LN. Juga berbagai keluhan lain. Hal-hal inilah yang menjadi raison detre. Namun, apakah semua keluhan ini memang faktanya demikian?
Mengenai keharusan membayar SPP/ berbagai iuran yang terlalu tinggi, hal ini adalah pertanyaan besar. Sebab tersedia banyak sekali beasiswa untuk jenjang S1, S2, ataupun S3. Jika kita ingin menggali informasi lebih mendalam, maka jalan ke arah itu akan bisa kita gapai. Bagi jenjang S1 misalnya, ada beasiswa Supersemar dan lainnya. Jenjang S2 ada beasiswa Supersemar. Sementara, untuk jenjang S3 ada beasiswa Habibie Center, misalnya.
Hanya, diperlukan keuletan ekstra memang untuk mendapatkan beasiswa ini. Namun melihat ada banyak mahasiswa yang bisa memperoleh akses ke beasiswa-beasiswa tersebut, rasanya tidak ada alasan untuk menjadi pesimis. Mahasiswa-mahasiswa yang dapat beasiswa tersebut, bukanlah mereka yang memiliki koneksi atau bagaimana, namun orang-orang biasa yang memang pekerja keras. Poinnya adalah, mereka pun bisa, maka dengan usaha pun kita semua pun juga bisa.
Lalu poin mengenai absennya program teaching/ research assistant seperti di LN. Apakah hal ini benar? Saya jelaskan dulu, makudnya program teaching/ research assistant adalah diterimanya seorang mahasiswa S2 dan S3 kedalam suatu kontrak kerja, yang biasanya diberikan beban kerja melakukan penelitian atau mengajar. Hal ini sudah sangat umum di LN, jadi mahasiswa pascasarjana di LN memang berstatus sebagai pekerja kontrak. Jadi, mereka tidak perlu memikirkan mengenai SPP atau
biaya penelitian, dan tinggal bekerja saja. Namun pertanyaannya, apakah di Indonesia sama sekali tidak ada program seperti ini? Jawabannya adalah tidak demikian. Negara kita pun juga sudah memiliki program teaching/ research assistant, dan beberapa perguruan tinggi top kita sudah menyediakan program seperti ini, terutama untuk ilmu alam atau engineering. Hanya, memang diperlukan penggalian informasi lebih lanjut untuk memperolehnya, namun dengan keuletan, maka informasi ini akan dengan mudah diperoleh.
Lalu poin bahwa terlalu lamanya pendidikan doktor dan jenjang menuju guru besar di tanah air juga tidak sepenuhnya benar. Pendidikan Tinggi kita sudah banyak menghasilkan doktor-doktor dalam usia muda, yang akhirnya mengabdi di berbagai instansi. Sementara, Indonesia pun juga sudah memiliki guru besar dalam usia muda. Sebut saja Prof Eko Prasodjo dari FISIP-UI, Prof Firmansyah dari FE-UI, Prof Ismunandar dari Kimia ITB, dan banyak lagi lainnya. Ketiga guru besar tersebut menjadi profesor di usia sebelum 40 tahun, dan menjadi guru besar karena kualitas kompetensi risetnya.
Mengenai poin, bahwa program pascasarjana hanya menjadi sapi perahan dosen-dosen kita, hal ini jelas tidak benar. Sudah dijelaskan diatas, bahwa sudah ada program teaching/ research assistant di beberapa perguruan tinggi tanah air, jadi otomatis dosen PT kita pun mendapat imbalan dari kualitas risetnya. Jika memang ada biaya yang harus dibayarkan ke dosen untuk setiap kelas yang dihadiri pada kuliah pascasarjana, kalau boleh jujur komponen biaya tersebut masih jauhlah lebih rendah daripada seminar-seminar yang diadakan oleh motivator bisnis. Jadi mengungkit-ungkit hal tersebut jelaslah sangat berlebihan, dan memberi kesan bahwa dosen mengambil uang mahasiswa.
Suatu hal yang tidak sepenuhnya benar, karena dosen tidak mendapatkan sebanyak yang dituduhkan. Jika adakan perbandingan, jangan bandingkan dengan imbalan dosen di LN, namun lakukan perbandingan dengan kondisi di lokal. Memang masalah uang adalah masalah peka, namun membesar-besarkan hal kecil jelas sangatlah tidak bijak. Tidak mungkin dosen di prodi apa pun menjadi kaya-raya, hanya dengan imbalan mengajar di pascasarjana. Jika ada dosen yang menjadi kaya-raya, itu bisa dipastikan karena yang bersangkutan menjadi konsultan di perusahaan atau industri, dan bukan karena mengambil uang mahasiswa.
Poin terakhir, adalah mudahnya mencari pekerjaan akademis di luar negeri. Hal ini juga tidak sepenuhnya benar. Mark Taylor pernah menulis di Nature News, bahwa pendidikan doktor di LN juga mengalami krisis. Tidak hanya di Amerika Serikat, namun di seluruh negara industri maju. Menurut Taylor, krisis ini terjadi karena para doktor berbondong-bondong untuk melamar posisi tenure track (posisi permanen) pada perguruan tinggi, yang akan diarahkan ke posisi guru besar.
Masalahnya, Tenure Track position itu jumlahnya terlalu terbatas, dan jelas tidak semua pelamar akan diterima. Hal ini juga tak lepas dari spesialisasi pada program doktor, yang menyebabkan seorang doktor hanya bisa melakukan satu pekerjaan spesialis tertentu. Saran dari Taylor, jelas supaya program doktor lebih multi-disipliner, sehingga bisa fleksibel menerima berbagai macam pekerjaan. Juga perlu ditekankan, bahwa doktor tidak harus bekerja di akademik. Industri strategis kita pun juga memerlukan doktor, dan ini terbukti ada doktor-doktor yang bekerja di industri farmasi/ bioteknologi kita. Gagal bekerja di akademis, bukanlah berarti bodoh, namun bisa jadi berarti tempat lain menjanjikan rezeki yang lebih baik.
Apakah Cukup Kita Berteriak-teriak?
Ini satu hal yang sangat kurang ditekankan, yaitu membangun entrepreneurship. Selalu dikeluhkan, bahwa biaya pendidikan kita terlalu tinggi, dan sangat memberatkan. Nah, jika demikian, mengapa tidak kita giatkan entrepreneurship, supaya bisa menutupi biaya mahal tersebut? Banyak orang yang melakukannya, mereka berwiraswasta, dan sukses membiayai anak-anak mereka untuk kuliah di kampus-kampus terbaik di negeri kita. Alasan tidak semua orang berbakat wiraswasta adalah alasan yang terlalu dicari-cari, dan pada dasarnya hanyalah pembenaran untuk tidak melakukan perubahan.
Bukalah mata, bahwa hanya dengan menggalakkan wirausahalah, maka itu memberikan solusi bagi masalah pendidikan kita. Saya berikan contoh, bahwa Nabi Muhammad SAW sendiri adalah seorang saudagar. Jadi menjadi saudagar, jika semua untuk niat yang mulia, jelas bukan sesuatu yang salah. Apalagi jika niat tersebut untuk membantu anak kita sendiri sekolah setinggi mungkin. Paradigma, bahwa hanya orang matre saja yang menjadi pengusaha haruslah dikikis, karena jelas ini sangat keliru. Nabi Muhammad SAW jelas sangat jauh dari sikap matre.
Tanpa banyak diketahui rekan-rekan di LN, sebenarnya birokrasi kita sudah mengalami reformasi habis-habisan. Walau masih banyak kekurangan di sana-sini, namun rekrutmen PNS sudah mulai profesional, dan memperhatikan kompetensi. Oleh karena itu, dinas kita sudah diisi oleh pegawai yang lebih berkualitas, dan banyak yang sudah master atau doktor dari universitas yang bagus. Walau masih banyak kekurangan sana-sini, namun kondisinya sudah jauh lebih baik daripada 10 tahun yang lalu. Salah satu terobosoan yang mereka lakukan adalah kerja samadengan Jerman, dengan
program debt swap. Program ini bertujuan mencetak 5.000 doktor kita di Universitas Jerman dalam waktu 10 tahun, dalam rangka meningkatkan kualitas perguruan tinggi kita. Kedepannya, diharapkan program ini membuat universitas di Indonesia akan mampu memproduksi doktor-doktornya secara mandiri.
Kita juga memerlukan solusi politik. Daripada kita teriak-teriak tanpa kasih solusi, ada baiknya kita mengawasi legislatif kita secara lebih baik, terutama pada komisi yang membawahi bidang pendidikan. Pengawasan itu bisa via LSM, lewat media/ pers, atau bisa juga dengan terjun langsung ke partai politik. Saya melihat, ada beberapa partai politik lokal yang bisa diteladani, karena mereka menerjunkan doktor-doktor ke dunia politik, dalam rangka memperbaiki berbagai masalah dalam pendidikan kita. Hal ini tidak ada salahnya, dan sah-sah saja. Jerman bisa menjadi contoh, karena banyak yang berkualifikasi doktor, menjadi anggota parlemen (bundestag).
Bukan right or wrong, its my country, atau sok menjadi nasionalis, namun hanya mencoba untuk obyektif. Pendidikan tinggi kita jelas memiliki banyak kekurangan. Namun menanggapinya dengan teriak-teriak, dan tidak memberi kontribusi positif untuk perbaikan, jelas tidak akan membantu apa pun. Di tengah semakin banyaknya keluhan dan celaan terhadap pendidikan tinggi kita, saya masih tetaplah optimis dengan dunia kampus kita, dan lebih memilih mencari solusi daripada teriak-teriak. Saya percaya, jika kita semua bekerjasama untuk menyelesaikan berbagai masalah
ini, tanpa perlu teriak-teriak, maka ada harapan braindrain tersebut kita ubah menjadi braingain.
- Arli Aditya Parikesit,M.Si adalah kandidat Doktor bidang Bioinformatika dari Universitas Leipzig, Jerman; peneliti di Departemen Kimia UI; dan Vice Editor-in-chief Netsains.com. Ia bisa dihubungi melalui akun @arli_ap di twitter.