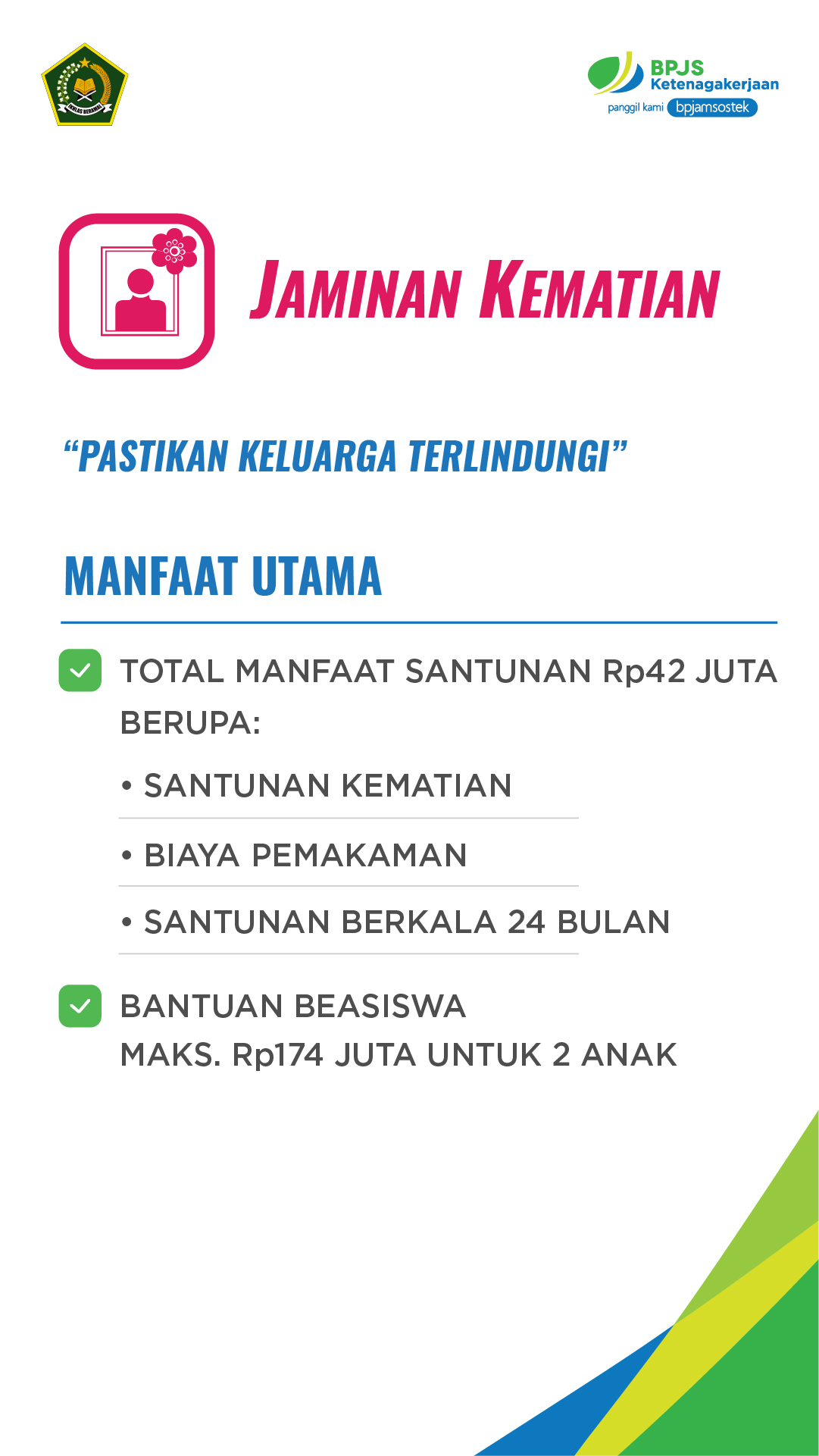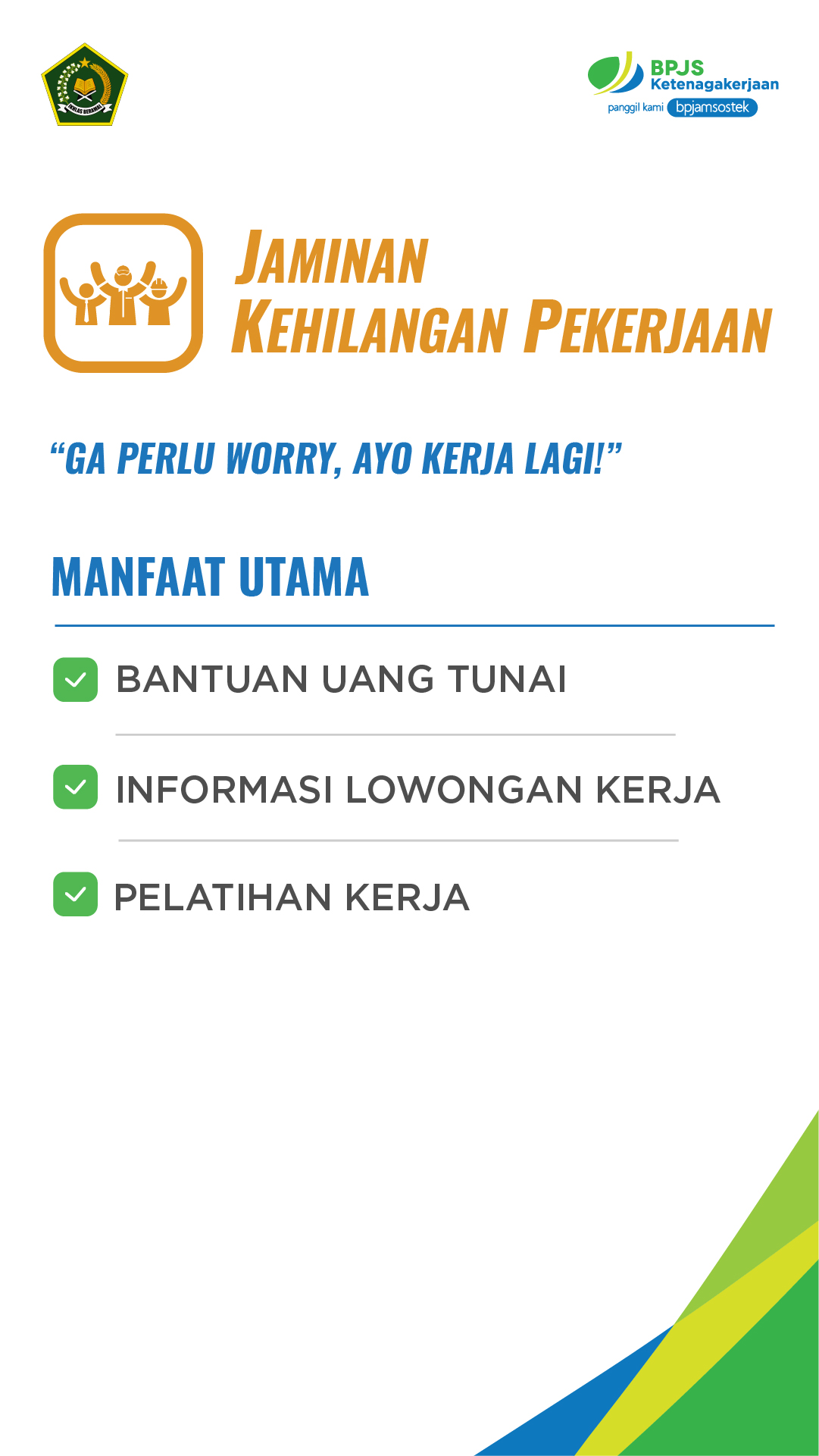Pudarnya Pesona Pendidikan Tinggi Indonesia
SIR ken Robinson, profesor pakar pendidikan dan kreativitas, sebagaimana dikutip oleh Yudistira Anm Massardi dalam tulisannya yang berjudul, Berhentilah Sekolah Sebelum terlambat, memberikan suatu gambaran betapa sekarang ini sudah terjadi inflasi gelar akademis sehingga ketersediannya melampaui tingkat kebutuhan.
Akibatnya, nilainya di dunia kerja semakin merosot. Lebih dari itu, ia menilai sekolah-sekolah hanya membunuh kreativitas para siswa. Maka, harus di lakukan revolusi di bidang pendidikan yang lebih mengutamakan pembangunan kreativitas.
Perlu digaris bawahi di sini adalah pembangunan Kreativitas. Berangkat dari pendidikan tinggi (baca: universitas) dosen memiliki peran yang cukup besar dalam upaya pembangunan kreativitas itu. Dosen harus mampu memberikan “sentuhan” kasih sayang ilmu yang tulus. Ada beberapa cara membangun kreativitas itu pertama, dengan melibatkan mahasiswa dalam proyek-proyek penelitian. Kedua, Berdiskusi aktif di luar kelas dengan para mahasiswa. Sehingga secara tidak langsung dosen telah mentransfer ilmu yang jauh berbeda dengan transfer ilmu di ruang kelas yang hampa itu.
Salah satu unsur yang terpenting dari pembangunan kreativitas mahasiswa adalah kebebasan akademis yang melekat di sendi-sendi akademisi. Pertanyaannya, apakah kebebasan akademis itu masih ada?
Lihat ke Dalam
Erichk Frimm, seorang sarjana psikologi terkenal dan salah seorang pengkritik sosial yang tajam. Dalam bukunya Mean for Him Self sebagaimana dikutip Buya Syafii Maarif (1980an), Frimm mempertentangkan dua macam etik. Pertama, etik humanistik yang rasional.
Menurut etik ini suatu otoritas adalah bersumber pada kemampuan manusia untuk memimpin atau menangani suatu tugas/jabatan. Si pengemban tugas ini dihormati orang semata-mata karena kualitasnya, oleh karena itu, ia tidak perlu melakukan intimidasi atau ancaman-ancaman, baik halus maupun kasar untuk menegakkan kepemimpinannya. Jadi “main” serba tertutup dan misteri adalah tabu menurut etik humanistik ini
Etik kedua adalah etik otoriter (authoriterian ethichs) yang akan dideskripsikan lebih lanjut an kira-kira bagaimana implikasinya bagi pendidikan pancasila. Etik otoriter sendiri punya dua kriteria. Pertama, formal dan kedua, material. Secara formal, etik otoriter menyangkal adanya kemampuan manusia untuk mengetahui yang baik dan yang buruk, yang bernilai dan yang tidak bernilai norma untuk itu selalu ditentukan oleh yang berkuasa yang mengatasi individu.
Sistem semacam ini tidak didasarkan atas akal sehat dan pengetahuan, tetapi atas citra kehebatan suatu otoritas dan atas perasaan lemah serta perasaan tergantung dari orang yang berada di bawah jaringan otoritas itu. Oleh karena itu keputusan-keputusan yang diambil tidak dapat dan tidak boleh di pertanyakan. Pokknya perintah atasan adalah sumber kebenaran.
Secara material, etik otoriter adalah untuk menjawab pertanyaan tetang yang baik atau yang buruk yang selalu di hubungkan dengan kepentingan yang berkuasa. Karena itu etik ini dengan sendirinya bersifat eksploitatif da sama sekali dapat membunuh kreativitas manusia pada umumnya. Menurut etik ini di antara dosa yang tidak di maafkan ialah sikap mempertanyakan terhadap keabsahan suatu keputusan atau kebijaksanaan yang telah diambil leh yang sedang berkuasa.
Bila kita jajarkan dalam perspektif yang lebih luas sebenarnya si penganut etik motoritas ini adalah orag yang tidak percaya kepada dirinya sendiri atau selalu merasa dalam posisi tidak aman. Oleh karena itu untuk menegakkan kewibawaan semuanya, berbagai cara yang tidak rasional di tepuh. Di antara cara itu ialah menempatkan orang-orang yang dalam bahasa Buya Syafii Maarif dikatakan spion-spion melayu.
Kemudian spion-spion melayu itu di tempatkan di berbagai unit untuk memonitori gerak gerik orang-orang yang dianggap tidak loyal kepada sistem otoriter yang notorius itu. Biasanya juga diturunkan ancaman lewat telepon, lewat jenjang kepegawaian, tidak diijinkan pergi keluar negeri dan lain-lain. penganut etik ini sangat takut menerima tenaga edukatif yang cerdas tetapi kriitis.
Kita kemudian berpendapat bahwa pada kenyataan semua orang bisa menyesuaikan diri dengan sistem yang kejam. Menurut Buya Syafii Maarif, terhadap sistem perbudakan pun manusia menyesuaikan diri, tetapi dengan pengorbanan status sebagai manusia merdeka. Untuk civitas akademika, mereka mungkin menyesuaikan diri, dengan membayar harga yang sangat mahal, yakni mengorbankan integritas intelektualnya.
Hubungan Penghambat
Bencana lain yang di alami oleh Perguruan Tinggi kita ialah di ciptakannya semacam hubungan patron-klien atau majikan-buruh antara pimpinan perguruan Tinggi atau dekan dengan para dosen. Hubungan patron-klien menurut buya syafii maarif adalah hubungan yang didasarkan atas hirarkis kekuasaan, bukan hubungan yang didasarkan hubungan kolegial-profesional.
Lebih lanjut Buya Syafii Maarif mengatakan bahaya dari corak hubungan semacam ini ialah munculnya pertunjukan hipokrit dari para dosen demi menjaga hari majikan agar konduitenya tetap dinyatakan baik. Sikap berpura-pura akan berjangkit di mana-mana. Para dosen kehilangan kepribadian. Kemana-mana mereka harus pakai topeng, apalagi bila di suatu kampus sang majikan telah siap dengan mata-matanya untuk memonior gerak-gerak dan ketaatan semua para dosen. Maka dapatlah dibayangkan sebagai akibat dari kecerobohan otoriter ini, Buya Syafii Maarif mengatakan bahwa perguruan tinggi kita telah agak lama kehilangan mahkotanya, yaitu kebebasan akademis.
Hubungan patron-klien di lingkungan kampus bukan saja telah merusak suasana kerja ilmiah, tapi telah merenggut hak yang paling asasi seorang dosen, yaitu kebebasan akademis sebagai suatu coditio sine qua non bagi usaha mencerdakan kehidupan bangsa.
Oleh: Febry Arisandi
Koordinator KSHI Research center.
Jurnalis LPM Gema Keadilan
Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
(//rhs)