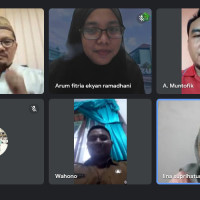Oleh: Emi Indra (GPAI SMPN 1 Palu, Sulteng)
Sinar terik memanggang punggung lelaki paruh baya itu. Sejak pagi ia telah mencangkul sawah yang tanahnya kering kerontong. Peluh membasahi wajahnya yang kecoklatan, sesekali ia menyekanya.
Rambut yang lurus terlihat tidak lagi terurus. Cangkul dan caping menjadi teman setia yang menemaninya setiap hari. Tak lupa bekal makan siang dan sebotol air minum yang telah disiapkan oleh sang istri.
Lelaki itu bernama Abdul. Seorang lelaki yang harus menghidupi keluarganya dari bertani. Tanah yang digarapnya adalah milik juragan kaya di kampung. Abdul beserta istri dan ke empat anaknya tinggal disebuah rumah panggung.
Rumah yang dibuat sejak menikahi seorang gadis tetangga kampung. Gadis itu bernama Rania. Kehidupan ekonomi rumah tangga mereka pas-pasan.
“Mas, hari ini mau ke sawah, ya?” tanya Rania kepada suaminya sambil mengaduk secangkir kopi. Kebiasaan Rania selepas salat subuh langsung ke dapur menyalakan tungku untuk menyiapkan sarapan.
“Ia, Dik, kan sudah menjadi kebiasaanku,” jawab Abdul kepada istrinya yang terlihat semakin gemuk setelah memiliki empat orang anak.
“Urus anak-anak, ya, Dik. Jangan sampai mereka tidak ke sekolah,” Abdul mengingatkan istrinya sebelum berangkat bekerja.
Dari hasil buah cintanya, mereka memiliki empat orang anak. Anak yang tertuanya bernama Rama, duduk di kelas 3 SMA. Yang kedua bernama Ilham, kelas 6 SD, sedangkan anak ketiga dan ke empat belum bersekolah.
Setiap hari Rama dan adiknya harus menempuh jarak 2 Km untuk sampai di sekolah dengan berjalan kaki. Mereka menyusuri pematang sawah sambil menenteng tas yang di dalamnya berisi buku, pensil dan sepatu. Mereka menggunakan sandal jepit karena takut sepatunya kotor. Mereka memakai sepatunya jika sekolah sudah dekat.
Meskipun hidup mereka bersahabat dengan kemiskinan, namun keinginan Abdul untuk menyekolahkan anak-anaknya sangatlah tinggi.
Setiap malam, Abdul bersama Rani selalu mendampingi anak-anaknya belajar. Selepas magrib, Abdul mengajari anaknya mengaji, sedangkan Rani mengajar membaca dan berhitung.
“Kamu harus sekolah, Nak. Cukup Bapak dan Emakmu yang tidak pernah menduduki bangku sekolah,” kata Abdul kepada Ilham setelah mengajarinya mengaji.
“Meski pun kita miskin, kamu harus bersekolah, Nak,” sambung Rania menyemangati anak-anaknya.
“Kalau aku bercita-cita menjadi dokter, apa boleh, Pah, Emak?” Rama melontarkan pertanyaan kepada orang tuanya dengan sopan.
“Bapak akan berusaha sekuat tenaga, Nak. Kamu harus mengangkat derajat keluarga. Dengan bersekolah tinggi, orang-orang tidak akan memandang kita sebelah mata, Nak,"
“Baiklah, Pak, Mak. Aku akan belajar bersungguh-sungguh agar bisa mendapatkan bea siswa untuk melanjutkan kuliah,” jawab Rama dengan penuh semangat dan optimis.
Abdul dan Rania selalu mengajarkan anak-anaknya bahwa Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum melainkan kaum itu sendiri yang akan mengubahnya. Abdul mengutip salah satu ayat dalam Al-Qur’an. Ayat ini yang menjadi andalan wejangan Abdul. Ayat ini pula yang menjadi pelecut buat Rama untuk rajin belajar dan membantu orang tuanya.
Setiap pulang sekolah dan hari minggu, Rama selalu membantu Bapaknya di sawah. Rama dengan senang hati meringankan pekerjaan Bapak dan Emaknya.
Kewajiban di sekolah juga tidak pernah ia tinggalkan. Semua PR yang diberikan oleh guru selalu diselesaikan saat malam hari. Hasil-hasil ulangannya pun selalu memuaskan. Di sekolah, Rama selalu menjadi bintang kelas bahkan menjadi siswa yang perolehan nilainya tertinggi dari semua siswa.
“Aku ingin jadi dokter, Man” kata Rama kepada sahabat karibnya Rahman ketika di kantin saat jam istirahat. Rahman yang selalu mengajak Rama untuk jajan di kantin karena Rama tidak pernah membawa uang jajan.
“Kamu pantas jadi dokter, kawan. Nilai-nilaimu selalu unggul di antara kami,” Rahman mendukung cita-cita Rama.
“Tapi, Man, apakah Bapakku sanggup membiayai kuliahku?” Rama kembali melontarkan pertanyaan yang sedikit pesimis.
“Pasti bisa. Apa kamu tidak ingat kata guru agama kita bahwa setiap mahluk mempunyai rezekinya masing-masing,” Rahman menjelaskan kembali apa yang telah disampaikan oleh Pak Soleh saat jam pelajaran agama.
“Aku harus mengubah nasib keluargaku, Man. Selama ini orang-orang tidak ada yang menghiraukan keluargaku, termasuk pamanku. Kami hanya dianggap sebagai makhluk yang tidak perlu ada di muka bumi ini. Begitu kali ya, Man, kalau kita miskin, anjing pun tak mau melihat,” Rama curhat ke Rahman tentang nasib keluarganya.
“Jangan berkata begitu, sahabatku. Tetaplah berusaha dan berdo’a. Hidup ini bagaikan roda berputar, kadang di atas terkadang di bawah. Boleh jadi hari ini kita tidak terpandang, namun jika Allah berkehendak besok atau lusa kita akan menjadi orang penting.” kata Rahman memberi semangat kepada Rama.
Di sekolah, hanya Rahman yang mau berteman dengan Rama. Mereka sahabat karib. Sahabat yang tidak memandang status sosial. Rama minder bergaul dengan teman-temanya.
Beruntung Rama mempunyai orang tua yang mahfum ilmu agama. Hinaan yang dilontarkan oleh keluarganya tak membuatnya patah semangat. Hinaan dijadikan sebagai motivasi untuk tetap bekerja. Keinginan untuk menyekolahkan anaknya yang selalu menguatkannya untuk bekerja apa saja asalkan halal.
Rani berasal dari keluarga yang terpandang . Orang tuanya memiliki harta benda yang cukup untuk menafkahi 3 turunan. Namun karena Rani kukuh menikah dengan Abdul, akhirya Rani tidak dihiraukan. Perbedaan status sosiallah yang menyebabkan Abdul tidak diterima seutuhnya oleh keluarga Rani. Namun kekuatan cinta mengalahkan segalanya. Cinta tak pandang status.
“Apa! Kamu mau jadi dokter? duit dari mana? Dari merampok?” ucap Kusno kepada Rama dengan nada tinggi. Rama memberanikan diri menyampaikan cita-citanya kepada pamannya saat datang ke rumah Rama. Kusno adalah kakak tertua Rani. Dialah yang sangat menentang pernikahan Rani dengan Abdul.
“Bapak akan berusaha mencari pekerjaan tambahan selain mengolah sawah. Aku juga berusaha mencari bea siswa agar bisa kuliah dengan gratis,” jawab Rama dengan muka memerah karena dibentak dan dipermalukan.
“Kamu jual kaki bapakmu pun tak akan cukup untuk menyekolahkanmu! tambah kaki Emakmu juga tak akan cukup. Untuk makan saja kamu selalu kekurangan, apalagi mau kuliah. Kamu Pikir kuliah di kedokteran itu murah?” kata paman dengan penuh sinis.
Kata-kata pedas yang dilontarkan oleh Kusno terdengar jelas oleh Abdul yang sementara mengaji di dapur. Bukan baru kali ini Kusno menghina adik iparnya. Setiap kali datang ke rumah Abdul pasti selalu meninggalkan luka batin. Kata-katanya selalu merendahkan.
Mendengar hinaan itu, Abdul hanya mengelus dadanya sambil bermohon kepada yang Maha membolak balikkan nasib. Kiranya Allah mengabulkan cita-cita Rama untuk menjadi dokter.
Begitu pun Rama saat diremehkan cita-citanya oleh pamannya. Sesungguhnya batinnya tidak menerima kata-kata itu, namun ia tetap yakin bahwa yang menentukan nasib itu Allah. Tugasnya hanya berusaha dan melangitkan doa.
Tibalah saatnya pengumuman kelulusan SMA. Rama tidak lagi tidur setelah melaksanakan salat tahajud. Lelaki yang mulai muncul jakun dan kumis titips itu mengambil Al-Qur’an sambil menunggu waktu salat subuh. Hatinya berdebar-debar menunggu hasil ujiannya. Sebelum matahari menampakkan batang hidungnya dari ufuk timur, Rama sudah berpamitan ke sekolah.
“Selamat, Nak Rama, kamu hebat. Kamu telah mengharumkan nama sekolah kita. Nilai tertinggi diraih oleh sekolah kita dan kamulah yang memperolehnya,” kata kepala sekolah diikuti riuh tepuk tangan seluruh siswa saat pengumuman kelulusan.
“Alhamdulillah ya Allah, Engkau mendengar doa-doaku,” gumam Rama dalam hati.
“Selamat ya, sahabatku. Aku selalu yakin, kamu pasti juaranya,” ujar Rahman sambil memeluk sahabat karibnya.
“Terima kasih, Man. Kamu yang selalu memberiku semangat. Kamu yang selalu mau mendengar curhatku dan kamulah sahabatku satu-satunya yang mau menerima aku tanpa melihat status sosialku.
Bulir-bulir bening yang menganak sungai jatuh di pipi pemuda yang berkulit coklat itu. Rasanya ia ingin segera pulang ke rumah agar bisa mengabarkan kebahagiaan ini kepada Bapak dan Emak.
Satu persatu guru-guru memberi ucapan selamat kepada Rama. Begitu pun teman-teman seangkatannya. Mereka semua bangga dan senang atas prestasi Rama. Rama yang selama ini diacuhkan sekarang menjadi pusat perhatian.
Setelah semua prosesi pengumuman dan pemberian cendra mata kepada yang memperoleh nilai tertinggi, Rama bergegas pulang ke rumah. Tak sabar lagi rasa bahagianya akan disampaikan kepada Bapak dan Emaknya.
“Pak, Emak, Rama lulus!” teriak Rama saat masih di tangga rumah panggung yang sudah mulai lapuk dimakan waktu.
“Alhamdulillah, Nak. Terima kasih ya Allah,” Bapak tak kalah senangnya mendengar kelulusan buah hatinya.
“Emak di mana, Pah?” tanya Rama kepada Bapak tentang keberadaan Emak.
“Emak pergi ke pasar, Nak. Sebentar lagi dia akan pulang.”
“Aku mau Emak segera tahu kabar ini, Pah,” kata Rama sambil meletakkan tas dan hadiah dari sekolah atas prestasinya.
Di tengah-tengah kebahagiaan anak dan bapaknya, tiba-tiba Sumi, tetangganya membuyarkan kebahagiaan mereka.
“Pak Abdul! Bu Rani … Bu Rani,” suara Sumi membuyarkan kebahagiaan Abdul dan Rama.
“Kenapa dengan istriku?” suara Abdul terdengar terbata-bata.
“Emak kenapa, Bi. Emak di mana?” Rama tak sabar lagi ingin mendengar kabar tentang Emaknya.
“Bu … Bu Rani ditabrak motor, Pak. Ia sudah dilarikan ke puskesmas,” kata Sumi dengan nada gugup.
“Ya Allah … Emak!” tangisan Rama pecah mendengar berita kecelakaan yang menimpa Emaknya.
Abdul dan Rama bergegas ke puskesmas dengan mengendarai sepeda. Didapatinya Emak terbaring dengan perban di pelipis dan kakinya. Emak sudah siuman. Lukanya tidak terlalu parah hanya sedikit lubang yang menganga di pelipis dan sudah dijahit oleh suster. Kakinya hanya lecet akibat terserempet motor yang melaju dari arah belakang saat emak naik sepeda menuju pasar.
Perawat telah membolehkan Emak pulang. Empat macam obat diberikan ke Emak. Suster memesan ke Abdul agar Emak meminum obatnya dengan rutin supaya lukanya segera mengering. Sebelum ke rumah, Emak meminta Rama untuk singgah terlebih dahulu ke rumah majikan tempatnya mencuci pakaian dan menyetrika. Emak takut dipecat jika tidak ada pemberitahuan perihal kecelakaan yang menimpanya.
Abdul dan Rani tak mengenal lelah untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Keinginan Abdul untuk menyekolahkan anak-anaknya menjadikannya tak mau dikalahkan oleh keadaan. “Aku pasti bisa, anakku pasti jadi dokter” Abdul selalu mengucapkannya saat bangun tidur. Sederatan afirmasi menjadi kalimat-kalimat wajib baginya.
“Pak, bagaimana kelanjutan sekolahku? Apa aku bisa lanjut kuliah?” tanya Rama sambil membawakan secangkin kopi ke Bapaknya.
“Maaf, Nak. Boleh, kan, tahun ini kamu istirahat dulu? In syaa Allah tahun depan kamu bisa daftar sekolah lagi,” jawab Abdul dengan rasa bersalah.
Abdul sangat berat menyampaikan ketidakmampuannya membiayai kuliah anaknya. Ia merasa sebagai bapak tidak bertanggung jawab. Semua pekerjaan untuk mendapatkan uang telah ia lakukan. Namun, tetap tidak cukup untuk membiayai kuliah anaknya.
Rania sebenarnya ingin meminta bantuan kepada saudara-saudaranya, tapi Abdul tidak mengizinkan. Cukup sudah hinaan mereka kepada keluarga Abdul. Tatapan sinis dan kata-kata Kusno yang pedis masih tersimpan rapi di memori Abdul. Kalimat “Jual kaki Bapakmu kalau kamu mau sekolah”, masih tergiang-ngiang di telinga Abdul.
Abdul berencana meminjam uang ke juragan tempatnya mengolah sawah. Di tengah-tengah lamunannya mencari solusi untuk mendapatkan biaya, tiba-tiba sebuah mobil Alphard berhenti di depan rumahnya.
“Assalamu alaikum, Dul,” suara sesorang dari dalam mobil yang duduk di belakang sopir sambil membuka kaca mobil. Lelaki itu memakai kaos berwarna putih yang dipadu dengan celana jeans berwarna abu-abu. Rambutnya yang rapi teracak karena hembusan angin sore.
“Waalaikumussalam,” jawab Abdul yang masih duduk di kursi kayu yang mulai lapuk. Ia tidak berdiri menyambut tamunya. Hanya mematung memperhatikan tamu yang datang tanpa diundang.
“Dul, ini aku, Rahmat, sahabat karibmu!” kata Rahmat dengan lantang. Abdul yang sedari tadi mematung, mengucek-ngecek matanya dan langsung berlari menghampiri Rahmat.
“Ya Allah, Mat. Kamu Rahmat, kan?” suara Abdul kegirangan sambil memeluk Rahmat. Mereka sahabat karib semasa kecil. Terpisah karena ayah Rahmat harus berpindah tugas ke Ibu Kota Negara. Rahmat menempuh pendidikan di Jakarta.
“Iya, Rahmat. Teman memancing di kolam Pak Darto. Kok Kamu lupa, Dul?” kata Rahmat diiringi ketawa lepas mereka berdua.
Abdul dan Rahmat larut dalam percakapan masa lalu yang telah mereka lewati. Dua sahabat ini seperti saudara kandung yang lama tak bersua, kini baru berjumpa. Rahmat menceriterakan kehidupan keluarganya yang diamanahi kekayaan oleh Allah, namun tidak diamanahi seorang anak. Usia perkawinannya sudah 20 tahun, tapi belum dikarunia seorang pun buah hati.
Rahmat menyampaikan keinginannya untuk membawa Rama ke Jakarta. Ia akan memasukkan Rama ke fakultas kedokteran di salah satu perguruan tinggi ternama.
“Dul, aku mohon agar kamu merelakan anakmu untuk menjadi anak angkatku. Aku akan mewujudkan cita-citanya menjadi dokter,” kata Rahmat dengan memelas.
“Alhamdulillah ya Allah. Engkau telah mengirimkan sahabatku sebagai bentuk terkabulnya do’aku. Keinginan anakku untuk menjadi dokter akhirnya tercapai. Makasih, Mat, kamu bersedia menyekolahkan anakku,” kata Abdul dengan mata berkaca-kaca sebagai pancaran hatinya yang mengharu biru.
Malam itu menjadi malam terindah buat keluarga Abdul. Rani, Rama dan adik-adiknya kembali melangitkan do’a sebagai ucapan syukur atas rezeki yang dilimpahkan ke keluarganya. Rani menyiapkan pakaian Rama yang akan dibawa ke Jakarta.
Keesokan harinya, Rahmat membawa Rama menjemput impiannya. Rama akan mewujudkan cita-citanya untuk mengangkat derajat keluarganya. Rama berjanji tidak akan menyia-nyiakan kesempatan yang telah Allah berikan.
Di kampus, Rama aktif mengikuti organisasi kemahasiswaan. Anak kampung ini menempa dirinya dalam berbagai kegiatan. Meskipun ia seorang aktifis kampus, namun nilai-nilainya selalu di atas rata-rata. Rama akhirnya bisa menyelesaikan studinya dengan predikat cumlaude.
Rama menjadi anak kebanggaan Rahmat. Lelaki yang berhati tulus ini meminta Rama untuk melanjutnya ke program pendidikan dokter spesialis. Rama memilih spesialis Ortopedi. Rama semakin sibuk dengan kuliahnya sambil praktek di Rumah Sakit. Dalam waktu empat tahun, gelar SpBO telah diraihnya dengan nilai sangat memuaskan.
Di RS tempatnya bekerja, Rama menjadi dokter andalan. Keahliannya menangani pasien-pasiennya menjadi buah bibir di dunia kesehatan. Berkat izin dari Allah, semua pasien yang ditanganinya sembuh. Kini dokter Rama, SpBO semakin sibuk dengan alat-alat bedah. Dokter tampan itu mendapat julukan, dokter bertangan dingin dan berhati malaikat.
Rama baru saja tiba di rumah, belum sempat beristirahat, tiba-tiba gawainya berdering.
“Dok, lagi di mana? ini ada pasien gawat!” suara terengah seorang suster seolah habis diburu sesuatu yang mengerikan.
“Baik, aku akan segera ke RS,” jawab Rama dengan singkat.
Rama belum juga rebahan, tapi sebagai dokter yang berdedikasi tinggi, keselamatan nyawa seseorang di atas segalanya. Rama meyakini bahwa menolong satu nyawa seperti menyelamatkan seluruh umat manusia. Tanpa pikir panjang, Rama segera berangkat ke RS.
“Dok, pasiennya harus diamputasi. Kanker tulang yang menggerogoti kakinya menyebabkan pasien tidak berhenti merintih kesakitan, Pasien telah kami masukkan di ruang operasi,” kata salah seorang dokter yang menangani pasien saat dilarikan ke RS.
“Baiklah, kalau memang seperti itu diagnosanya, bismillah kita operasi sekarang,” jawab dokter Rama.
Rama bergegas masuk ke ruangan bedah untuk menyelamatkan pasien yang sudah bersiap-siap di meja operasi. Betapa terkejutnya Rama saat pandangannya melihat pasien.
“Ya Allah … Ini Pamanku! Siapa yang membawanya ke sini?” tanya Rama sambil menyengap dengan tangan. Ia terkesiap melihat yang terbaring itu adalah Kusno.
“Dia dibawa oleh seorang ibu yang rambutnya sebagian sudah memutih,” jawab salah seorang dokter yang lengkap dengan baju bedahnya.
Dokter Rama dan beberapa orang dokter lainnya mulai mengerjakan tugasnya dengan penuh kehati-hatian. Operasi selama dua jam berjalan dengan lancar. Setelah pasien siuman, segera dibawa ke ruang perawatan.
Setiap pagi Rama berkeliling mengunjungi kamar pasien-pasiennya termasuk kamar Kusno. Selain mengecek perkembangan kesehatan pasien, juga memberikan support kepada pasien agar segera sembuh.
“Ra … Rama, kan? Kamu, nak Rama?” tanya Kusno dengan muka pucat. Ia tidak menyangka kalau yang mengunjunginya adalah Rama. Rama anak kampung yang sangat diremehkannya dulu.
“Iya, aku Rama, Paman. Akulah yang mengoperasi kaki paman,” jawab Rama dengan penuh santun. Tak sedikit pun terpancar rona marah di wajah Rama.
“Maafkan aku, Nak. Aku telah merendahkanmu dulu. Maafkan kata-kata paman ketika kamu menyampaikan cita-citamu untuk menjadi dokter. Ternyata kaki Bapakmu tidak dijual untuk menjadikanmu seorang dokter ahli. Justru kaki paman sekarang yang harus diamputasi,” kata Kusno dengan linangan air mata penyesalan.
“Aku telah memaafkan paman dari dulu. Aku yang harus berterima kasih ke paman. Dengan kata-kata itulah, aku sekarang menjadi dokter. Aku ingin membuktikan bahwa tanpa menjual kaki Bapak, aku bisa menjadi dokter,” jawab Rama sambil memeluk pamannya.
Keduanya larut dalam keharuan. Mereka bersama-sama kembali mengenang masa-masa di kampung. Tidak ada yang mustahil jika Allah berkehendak. Tetaplah berusaha sambil selalu melangitkan doa. Jalani hidup tanpa banyak berkeluh kesah, perkuat otot syukur sebagai bentuk terima kasih ke Sang Maha Pemberi Nikmat. Ubahlah cemoohan dengan tepuk tangan.