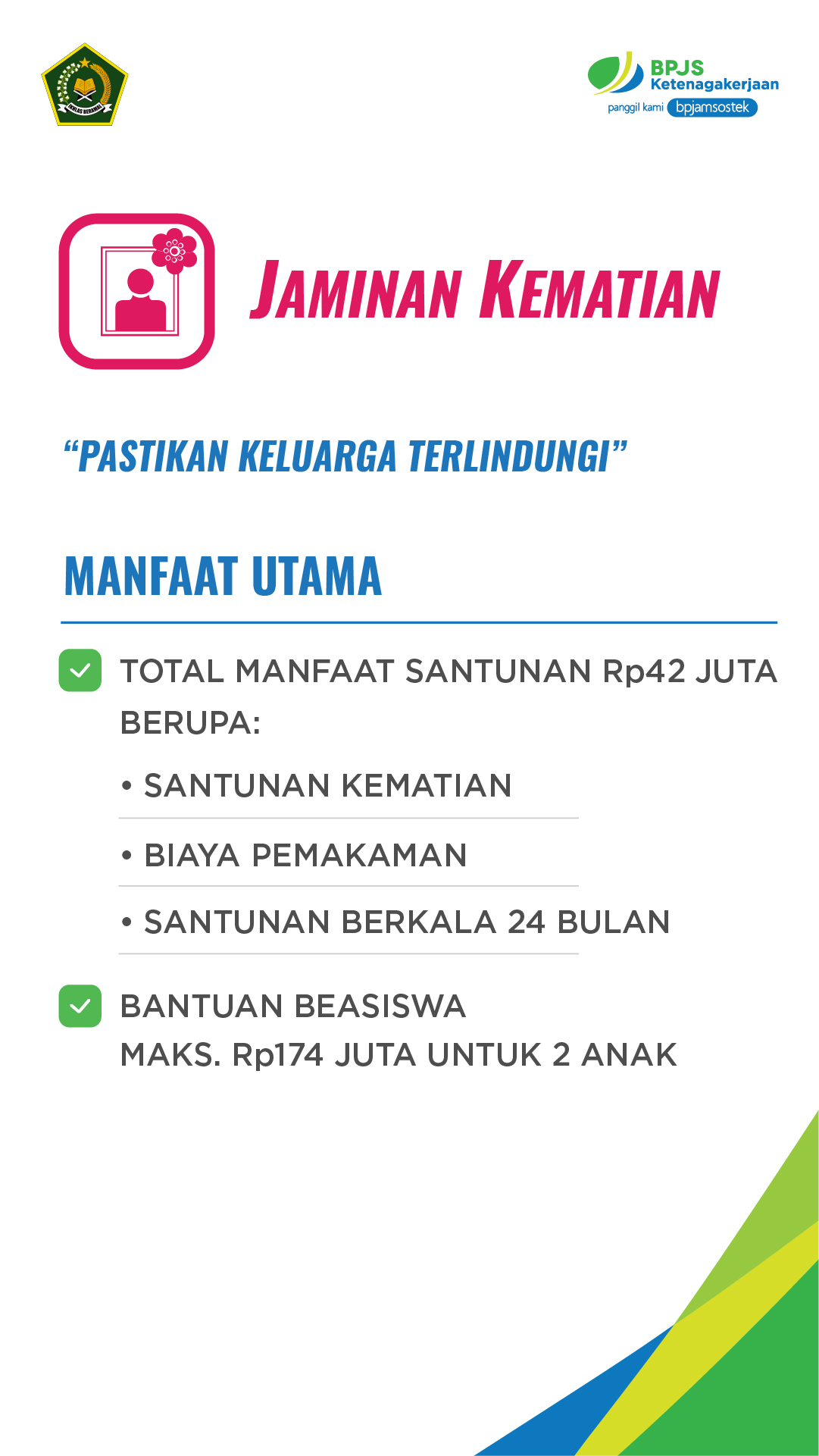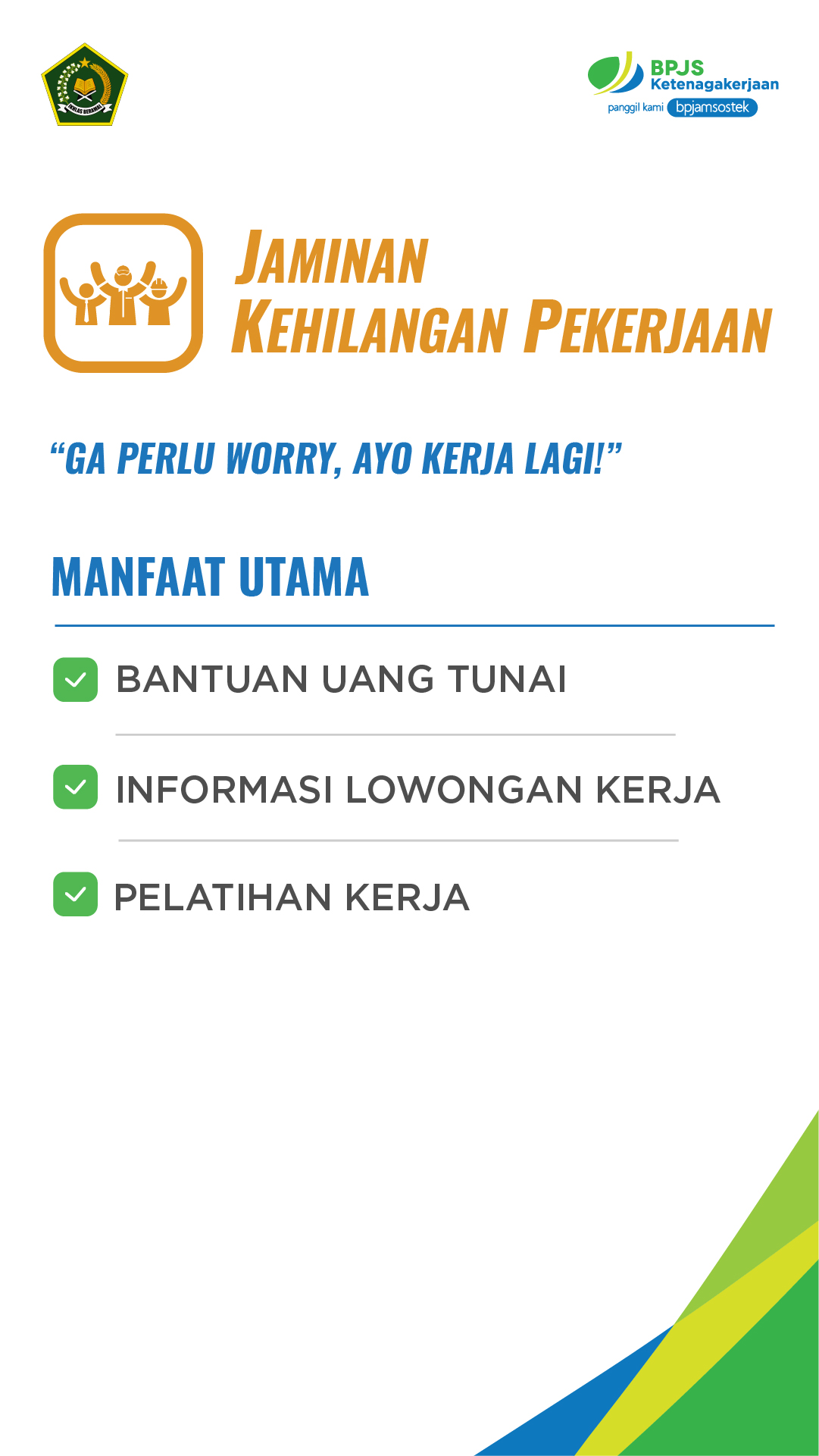Renungan MENJELANG Hari Lahir Pancasila 1 Juni 1945 ; Mencari Pancasila yang ’Ketlingsut’
Pancasila terangkat dalam wacana publik seakan kita sedang mencari sesuatu benda yang “ketlingsut.” Pancasila itu bukan hanya milik kita tetapi terlebih adalah diri kita, yakni diri kebangsaan, diri keindonesiaan yang seturut von Savigny:” setiap bangsa itu memiliki jiwanya masing- masing yang disebut volkgeist.” Juga Ernest Renan menegaskan:” Une nation est une ame, een natie is een ziel (bangsa itu satu jiwa, bangsa itu mempunyai jiwanya sendiri.” (Soekarno, “Lahirnya Pancasila,” 1945).
Wacana publik tadi kini terlembaga melalui tekad MPR di bawah Taufiq Kiemas yang memopulerkan “empat pilar” bernegara yang terdiri atas Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Tentu saja tekad itu benar dan mulia, yang diikuti dengan berbagai sosialisasi dan pertemuan ilmiah maupun sarasehan, ada pula lomba pidato dan sayembara tulisan bertopik ke empat pilar tersebut.
Penulis mencoba berpendapat lain di depan Rapim MPR 12 Nopember 2009 dimana sistematika empat pilar itu pada dasarnya adalah interpretasi MPR. Jika term empat pilar boleh diidentikkan dengan sokoguru perumahan model Jawa klasik, tiap- tiap pilarnya mempunyai status dan fungsi sebanding, tidak ada yang lebih dan tidak ada yang kurang. Roboh satu di antaranya akan sangat membahayakan perumahan yang ditopang.
Di sinilah Pancasila kurang pas disebut pilar dan dalam kritik penulis, Pancasila tereduksi bila hanya disejajarkan dengan ke tiga pilar yang lain karena justru Pancasilalah sumber nilai dari UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Bila NKRI suatu saat berubah menjadi RIS seperti yang dalam sidang BPUPKI dikehendaki oleh Bung Hatta; Pancasila akan tetap menjadi sumber filsafat dan ideologi Negara RIS itu.
Bhinneka Tunggal Ika, secara akademik setara mono-pluralisme sebagai hakikat manusia yang menjadi pendukung sila-sila Pancasila (Notonagoro, 1975), dus— ia bukanlah dasar dan ideologi Negara. Pancasila adalah pondasi di bawah pilar- pilar yang tiga tersebut. Walhasil, interpretasi MPR tersebut belum tentu valid secara akademik, tetapi “kadung” diterima secara popular.
Jelas agaknya bahwa dua problem pokok terbengkelainya Pancasila dalam hidup kenegarabangsaan terletak pada dua hal; problem interpretasi dan problem implementasi. Soal pertama sangatlah mendasar sebab kemulusan pemecahan persoalan ke dua akan bergantung kepadanya. Namun pemecahan problem interpretasi pun tidak akan berjalan dengan mudah khususnya dalam fakta keterbatasan pengetahuan kolektif untuk itu. Bila interpetasi sangat bergantung kepada keandalan (ilmu) pengetahuan, problem implementasi lebih dominan terletak pada kejelasan kehendak atau kemauan, semacam political will.
Mengikuti AMW Pranarka (1985), yang mendesak untuk diklarifikasi seturut elaborasi akademik Pancasila adalah problem epistemologis, yakni persoalan tentang model kepengetahuan tentang Pancasila. Pranarka membedakan empat jenis epistemologi Pancasila, yakni: Pancasila ilmiah, Pancasila ideologis, Pancasila filosofis dan Pancasila Theologis.
Jauh sebelum penelitian Pranarka, Notonagoro sudah menukik lebih dalam melalui perenungannya bahwa selain dimensi ideologis,ilmiah dan filosofis, juga dimungkinkan adanya “Mistik Pancasila.” Barangkali bisa terjadi kesalahpahaman terkait dengan salah persepsi dimana “mistik” sering diserupakan dengan “klenik.” Namun bila dibaca buku- buku Fritjof Capra, Donald Walter dan Michael Talbott, William Johnston, Roger Walsh, yang menunjukkan adanya krisis keilmuan modern dan krisis rasionalitas Barat; Notonagoro mendahului mereka.
Kesemua cendekiawan asing itu sampai pada pentingnya wacana mistik Timur sebagai “jalan keluar” dari kemacetan pemikiran ilmiah khususnya yang dikawal oleh ilmu Fisika. Dalam karyanya “The Turning Point,” (1982;67) Capra menulis: ”An increasing number of scientists are aware that mystical thought provides a consistent and relevant philosophical background to the theories of contemporary science.”
Tulisan ini hanya ingin menyerukan satu jalur interpretasi Pancasila demi orisinalitas dan konsistensi pengamalannya; yakni bahwa berbicara tentang Pancasila mustahil dipisahkan dari pidato Bung Karno 1 Juni 1945 di depan sidang BPUPKI. Penulis tak sependapat bahwa Pancasila itu “karya bersama;” —Pancasila adalah temuan Soekarno. Bandingkan dengan Wage Rudolf Soepratman, dia menciptakan lagu “Indonesia Raya” juga dengan koreksian dan saran teman- temannya tetapi sejarah mengabadikan lagu kebangsaan itu sebagai karya seorang W.R Supratman.
Bila rejim Orde Baru dengan politik de-sukarnoisasinya mengeliminasi Pancasila 1 Juni 1945 itu misalnya dengan menolak pemerasan Pancasila menjadi Trisila dan Ekasila sebagaimana termuat dalam pidato tersebut, justru Trisila dan Ekasila itulah memberikan jalan bagi interpretasi Pancasila. Rasionalitasnya adalah seperti berikut.
Dalam makalah pembanding yang penulis ajukan terhadap (alm.) Prof Kuntowijoyo saat diskusi di Pusat Studi Kebijakan Yogyakarta beberapa tahun silam, dimana Trisila dan Ekasila juga dipinggirkan, penulis merespons bahwa dalam pidato 1 Juni 1945 itu Bung Karno berbicara secara filosofis, ideologis, tetapi juga metaforis-hiperbol. (Bersambung hal 13)-s
Pemerasan Pancasila dapat disikapi secara metaforis guna memudahkan khalayak mengerti apa sesungguhnya Pancasila yang ditawarkannya dalam sidang BPUPKI itu. Namun yang terpokok adalah nada filosofis dimana “pemerasan” justru membuktikan watak sistemik Pancasila, dengan disiplin pikiran berjenjang guna sampai pada hakikatnya.
Watak sistemik khususnya secara substantif, adalah kriteria suatu filsafat; dus, dengan Trisila dan Ekasila (esensi Pancasila) Bung Karno sungguh menunjukkan kelihaian pikirannya bahwa Pancasila adalah sistem filsafat. Atas respons penulis, Prof.Kuntowijoyo melalui “penerjemahnya” – Susilaningsih,MA—menyetujui pikiran penulis. Maka itu secara hermeneutik, penafsiran Pancasila dapat dengan lebih ringan dimulai dari falsafah gotongroyong sebagai Ekasila; dan Sosio-nasionalisme, Sosio-demokrasi dan Ketuhanan sebagai Trisilanya. Secara akal sehat pun diukur dari Trisila dan Ekasila, implementasi Pancasila sampai hari ini merah nilai raportnya.
“Pelaksanaan” Pancasila selama ini, khususnya sejak rejim Soekarno, Soeharto dan Reformasi, jauh dari pendekatan tersebut. Soekarno sendiri sebagai kepala Negara nyata-nyata mereduksi Pancasila menjadi revolusi Indonesia dimana Pancasila Soekarno dikebiri oleh Soekarnoismenya. Soeharto mereduksi Pancasila menjadi “pembangunan” dimana konsep pembangunan dikuruskan ke arah tafsir pembangunan ekonomi, lebih miskin lagi menjadi pertumbuhan ekonomi. Menurut Daoed Yoesoef, angka statistik pertumbuhan ekonomi pada dasarnya adalah fiktif.
Rejim Reformasi sama sekali tidak ada kemauan untuk melaksanakan Pancasila berhubung dengan kebohongan publiknya yang kian menyala. q - s. (2946-2011).
*) Slamet Sutrisno, Pengajar Pendidikan Pancasila di UGM.