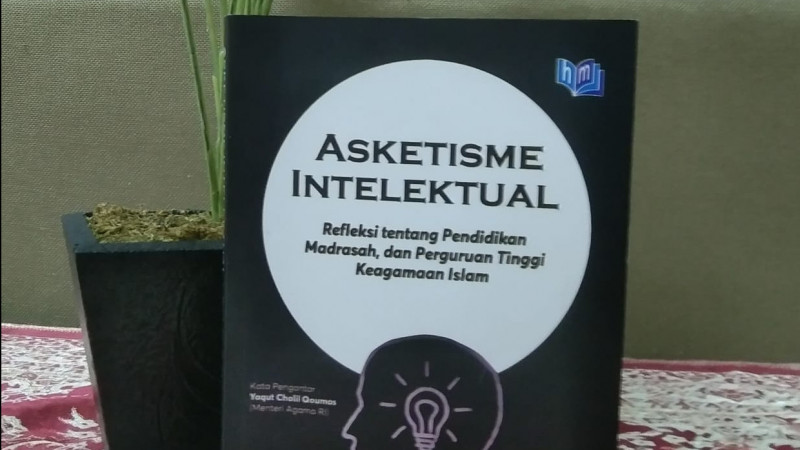
Cover buku Asketisme Intelektual
Judul Buku: Asketisme Intelektual, Refleksi tentang Pendidikan Madrasah dan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam
Penerbit: Halaman Moeka Publishing
Jumlah halaman: xii+235 hal
Tahun penerbitan: 2023
"Menulis adalah bekerja untuk keabadian", demikian ungkapan begawan sastra Pramoedya Ananta Toer tentang pandangannya mengenai dunia tulis-menulis.
Dengan menulis, lanjut pemilik karya monumental "Bumi Manusia" ini, seorang manusia tidak akan hilang dari pusaran sejarah. Pandangan Pram tersebut terasa begitu relevan dalam berbagai konteks sosial budaya hingga hari ini, termasuk dalam aspek penguatan Pendidikan Islam.
Menulis, dalam perspektif yang lebih luas adalah tentang bagaimana merawat eksistensi diri dalam ranah intelektualitas melalui membaca, menulis itu sendiri, dan memiliki buku. Ini adalah wilayah yang sangat subversif dalam diri seseorang. Itulah mengapa Azyumardi Azra (2012) menyebutnya sebagai akun personal (personal account) untuk mengidentifikasi bahwa ruang pribadi tersebut mengandung tanggung jawab personal yang melampaui banyak hal.
Di antara yang terlampaui itu berupa perenungan mendalam yang berakar dari perjalanan tugas dan refleksi intelektual di dalamnya. Salah satu contohnya adalah Isom Yusqi. Guru Besar Tafsir UIN Jakarta yang saat ini juga menjabat Direktur KSKK Kemenag, menulis dengan tangkas dalam apa yang disebutnya sebagai sebuah buku antologi pemikiran.
Buku Asketisme Intelektual, Refleksi tentang Pendidikan Madrasah dan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (2023) ini bisa jadi terkait upaya tiada akhir dalam konteks pendidikan Islam. Menariknya, buku ini hadir sebagai representasi ide penulis sekaligus memunculkan kritik bernas di dalamnya.
Dalam pengantar buku ini, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menilai sosok Isom sebagai figur yang layak menuangkan gagasan dan pemikirannya di bidang pendidikan Islam berdasar pengalaman panjangnya di berbagai unit kerja di Kemenag. Dengan kualifikasi tersebut, pria yang akrab disapa Gus Men ini meyakini, dan senada dengan Pramudya di atas, bahwa apa yang ditulis dalam buku ini sebagai ide akan memiliki daya melintas waktu sebagai legacy intelektualitas.
Saat merangkai pandangannya tentang Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, penulis menilai bahwa saat ini tengah terjadi mentalitas selaku konsumen pengetahuan produk ilmuwan dan cendekiawan luar negeri. Penulis mengharapkan lahirnya invention-invention pemikir nusantara yang, baginya, telah lama hilang dan tidak lahir kembali (hal. 158). Menurutnya, invention tersebut idealnya hadir dari para pemikir-ulama yang mampu berlaku asketik dari godaan jabatan, uang, dan kelimpahan sesaat.
Di titik pandang ini, pembaca seperti diantarkan langsung maupun tidak langsung pada tilikan Profesor Ahmed T Kuru dalam Islam, Authoritarianism, and Underdevelopment: A Global and Historical Comparison (2019), buku ekstensif yang sempat menjadi bahasan di mana-mana. Jika Isom menera tentang kecenderungan hilangnya asketisme cendekiawan-ulama, Kuru menegaskan inferiotas ulama dan pilihan untuk "perselingkuhan" mereka dengan kuasa dan borjuasi. Meski berbeda, keduanya sama-sama memiliki kegelisahan terhadap menurunnya peran strategis kaum ulama dan cendekiawan dalam relasi kekuasaan dan godaan sesaat.
Sebagai catatan, buku ini memiliki beberapa hal yang dapat ditemukan, di antaranya adalah problem elaborasi ide. Ketika berbicara tentang transformasi digital di madrasah, misalnya, konstruksi bangunan ide yang ditawarkan terasa menemui jalan yang belum sampai di ujung puncak pengetahuan. Saat menuangkan gagasan tentang maturitas digital sebagai prasyarat membangun kemandirian dalam transformasi digital, pola yang hendak ditempuh untuk mencapai kondisi ideal tersebut melalui integrasi cyber pedagogy dan cyber technology.
"Duo" cybernetika ini memang menjadi pilihan rasional, namun juga mencemaskan. Saat ini, keterhubungan dalam segala hal terkait hajat hidup manusia memang diwarnai hal serba otomatisasi dan digitalisme. Akan tetapi, segala "nikmat" digital ini bukan tanpa masalah.
Pasalnya, tanpa pemahaman dan kesadaran (concsiousness) yang memadai dan tepat, teknologi dan digitalisme bisa menjadi "tuan" yang menakutkan dengan potensi penuhanan segala hal terhadapnya. Kita tahu, heboh dan mengamuknya teknologi OpenAI (Artificial intelligent) dalam beragam rupa perkembangnnya, pelan tapi pasti telah mampu meminggirkan peran dan fungsi berpikir manusia.
Itulah mengapa, perubahan pada dasarnya adalah tentang mengubah pola pikir (mindset). Pembudayaan digitalisme yang hendak dibangun dalam konteks madrasah idealnya dibangun dengan strategi perubahan dari pola pikir entitas madrasah itu sendiri. Perubahan cara berpikir ini penting karena digitalisme bukanlah sebuah panggung sulap yang seketika mampu merubah realitas. Pola pikir akan menggerakkan dan memaknai dengan tepat bagaimana perubahan yang akan dijalankan tanpa kehilangan jati diri sebagai madrasah.
Catatan lainnya adalah tentang konsistensi tema. Buku ini tidak membuat peta dan penempatan tema yang disesuaikan menurut nomenklatur. Misalnya saja, tema tentang madrasah dan pesantren digabung dalam satu frame yakni refleksi tentang pendidikan madrasah.
Contohnya, saat bicara tentang transformasi digital di madrasah (hal. 3) hingga konteks moderasi beragama di madrasah (hal.73), konsentrasi pembaca bergeser ke prinsip epistemologi keilmuan di pesantren (hal. 79) lalu kembali lagi ke konteks madrasah dengan bahasan mengenai Evaluasi Diri Madrasah (EDM) serta Electronic Rencana Kerja dan Anggaran Madrasah (e-RKAM) pada halaman selanjutnya. Akibatnya konsentrasi pembaca seperti maju-mundur dengan tebaran ide yang disajikan.
Beberapa catatan tersebut tidak mengurangi atribusi penulis sebagai pejabat-pemikir dengan karya yang menggugah kesadaran bersama terhadap perlunya adaptasi dan mitigasi perubahan ini.
Saiful Maarif (Bekerja pada Subdit PAI pada PAUD/TK, Asesor SDM Aparatur Kemenag)
Bagikan: